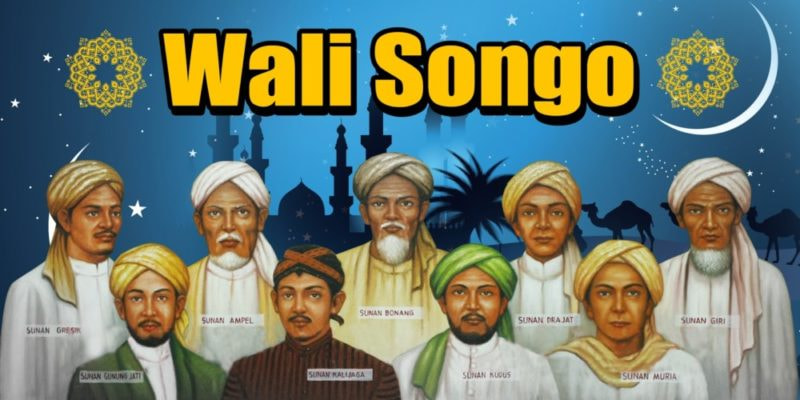Assalamualaikum,
Pak Ustadz, saya ingin bertanya aturan dalam mengharamkan sesuatu masalah. Apakah sebaiknya kita mengharamkan hal-hal yang tidak ada dalilnya, ataukah kita halalkan saja?
Sebab saya takut terkena hukum dosa bila mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bukankah sebaiknya kita menghindari yang haram?
Demikian semoga ustad bisa menjelaskan dengan jelas. Terima kasih
Assalamu ‘alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Dalam menetapkan hukum syariah atas setiap perkara, ada prinsip yang paling dasar yang menjadi pegangan. Prinsip ini sesungguhnya bagian dari kaidah fiqhiyah yang lafadznya adalah:
الأصل في الأشياء الإباحة
Hukum asal pada sesuatu adalah kebolehan
Dari kaidah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal sesuatu perkara selalu halal hukumnya, boleh dikerjakan dan mubah kedudukannya. Fiqih Islam selalu memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci dan tidak dimurkai Allah SWT.
Kecuali setelah adanya dalil nash yang shahih (valid) dan sharih (tegas) dari Allah SWT sebagai Asy-Syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau makruh.
Namun sampai kapan pun selama tidak ada nash yang shahih –misalnya karena ada sebagian Hadis lemah– atau tidak ada nash yang sharih yang menunjukkan haram, maka hukum dasar setiap masalah itu selalu mengacu kepada tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah, boleh, halal.
Demikianlah para ulama-ulama Islam sepanjang zaman mendasarkan setiap ketetapan hukum, fatwa, sera dalam memutuskan banyak perkara umat manusia.
Dasar Hukum
Dalil ayat-ayat al-Quran yang antara lain:
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
Dialah yang menjadikan UNTUKMU bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, (Q. Al-Baqarah: 29)
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه
"(Allah) telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya daripadaNya." (QS. Al-Jatsiyah: 13)
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
"Belum tahukah kamu, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak." (QS. Luqman: 20)
Ketiga ayat di atas jelas dan tegas menyebutkan bahwa Allah SWT telah menyerahkan segala sesuatu di bumi ini untuk manusia. Inilah dalil tentang kehalalan segala sesuatu. Dan Allah tidak akan membuat segala-galanya ini yang diserahkan kepada manusia dan dikurniakannya, kemudian Dia sendiri mengharamkannya. Kalau tidak begitu, buat apa Ia jadikan, Dia serahkan kepada manusia dan Dia kurniakannya?
Beberapa hal yang Allah haramkan itu, justeru karena ada sebab dan hikmat, yang –insya Allah– akan kita sebutkan nanti.
Dengan demikian arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit. Sedangkan arena halal justru sangat luas. Sebab nash-nash yang sahih dan tegas untuk mengharamkan, jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, jumlahnya sangat banyak.
Dan hukumnya kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dimaafkan Allah.
Untuk soal ini ada satu Hadis yang menyatakan sebagai berikut:
ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا (وما كان ربك نسيا
"Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (dimaafkan). Oleh karena itu terimalah permaafan dari Allah, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun." Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa.(Riwayat Hakim dan Bazzar)
وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال, "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم
Dari Salman Al-Farisy bahwa Rasulullah saw pernah ditanya tentang hukumnya samin, keju dan keledai hutan, maka jawab beliau: Yang halal adalah sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya dan yang disebut haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya. Sedang apa yang Allah diamkan, maka dia itu salah satu yang Allah maafkan buat kamu." (Riwayat Tarmizi dan lbnu Majah)
Rasulullah tidak ingin memberikan jawaban kepada si penanya dengan menerangkan satu persatunya, tetapi beliau mengembalikan kepada suatu kaidah yang kiranya dengan kaidah itu mereka dapat diharamkan Allah, sedang lainnya halal dan baik.
Dan sabda beliau juga,
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu menyia-nyiakannya dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka jangan kamu langgar. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan dia. Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia." (Riwayat Daraquthni, dihasankan oleh an-Nawawi)
Kaidah asal segala sesuatu adalah halal ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi meliputi masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk daripada urusan ibadah, yaitu yang biasa kita istilahkan dengan adat atau mu’amalat.
Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat, kecuali sesuatu yang memang oleh syari’ sendiri telah diharamkan dan dikonkritkannya sesuai dengan firman Allah:
وقد فصل لكم ما حرم عليكم
"Dan Allah telah memerinci kepadamu sesuatu yang Ia telah haramkan atas kamu." (QS. Al-An’am: 119)
Ayat ini umum, meliputi soal-coal makanan, perbuatan dan lain-lain.
Berbeda sekali dengan urusan ibadah. Dia itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan, melainkan dari jalan wahyu. Untuk itulah, maka terdapat dalam suatu Hadis Nabi yang mengatakan:
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
"Barangsiapa membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak." (Riwayat Bukhari dan Muslim)
Ini, adalah karena hakikat AGAMA –atau katakanlah IBADAH– itu tercermin dalam dua hal, yaitu:
Hanya Allah lah yang disembah.
Untuk menyembah Allah, hanya dapat dilakukan menurut apa yang disyariatkannya. Oleh karena itu, barangsiapa mengada-ada suatu cara ibadah yang timbul dari dirinya sendiri –apapun macamnya– adalah suatu kesesatan yang harus ditolak. Sebab hanya syari’lah yang berhak menentukan cara ibadah yang dapat dipakai untuk bertaqarrub kepadaNya.
Adapun masalah Adat atau Mu’amalat, sumbernya bukan dari syari’, tetapi manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Syari’ dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan, meluruskan, mendidik dan mengakui, kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan mudharat.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya sikap manusia, baik yang berbentuk omongan ataupun perbuatan ada dua macam: ibadah untuk kemaslahatan agamanya, dan kedua adat (kebiasaan) yang sangat mereka butuhkan demi kemaslahatan dunia mereka Maka dengan terperincinya pokok-pokok syariat, kita dapat mengakui, bahwa seluruh ibadah yang telah dibenarkannya, hanya dapat ditetapkan dengan ketentuan syara’ itu sendiri."
Adapun masalah Adat yaitu yang biasa dipakai ummat manusia demi kemaslahatan dunia mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, semula tidak terlarang. Semuanya boleh, kecuali hal-hal yang oleh Allah dilarangnya Demikian itu adalah karena perintah dan larangan, kedua-duanya disyariatkan Allah. Sedang ibadah adalah termasuk yang mesti diperintah. Oleh karena itu sesuatu, yang tidak diperintah, bagaimana mungkin dihukumi terlarang.
Imam Ahmad dan beberapa ahli fiqih lainnya berpendapat: pokok dalam urusan ibadah adalah tauqif (bersumber pada ketetapan Allah dan Rasul). Oleh karena itu ibadah tersebut tidak boleh dikerjakan, kecuali kalau ternyata telah disyariatkan oleh Allah. Kalau tidak demikian, berarti kita akan termasuk dalam apa yang disebutkan Allah:
م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
"Apakah mereka itu mempunyai sekutu yang mengadakan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah?" (QS. As-Syura: 21)
Sedang dalam persoalan Adat prinsipnya boleh. Tidak satupun yang terlarang, kecuali yang memang telah diharamkan. Kalau tidak demikian, maka kita akan termasuk dalam apa yang dikatakan Allah:
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا
"Katakanlah! Apakah kamu sudah mengetahui sesuatu yang diturunkan Allah untuk kamu daripada rezeki, kemudian kamu jadikan daripadanya itu haram dan halal? Katakanlah! Apakah Allah telah memberi izin kepadamu, ataukah kamu memang berdusta atas (nama) Allah?" (QS. Yunus: 59)
Ini adalah suatu kaidah yang besar sekali manfaatnya. Dengan dasar itu pula kami berpendapat: bahwa jual-bell, hibah, sewa-menyewa dan lain-lain adat yang selalu dibutuhkan manusia untuk mengatur kehidupan mereka seperti makan, minum dan pakaian. Agama membawakan beberapa etika yang sangat baik sekali, yaitu mana yang sekiranya membawa bahaya, diharamkan; sedang yang mesti, diwajibkannya. Yang tidak layak, dimakruhkan; sedang yang jelas membawa maslahah, disunnatkan.
Dengan dasar itulah maka manusia dapat melakukan jual-beli dan sewa-menyewa sesuka hatinya, selama dia itu tidak diharamkan oleh syara’. Begitu juga mereka bisa makan dan minum sesukanya, selama dia itu tidak diharamkan oleh syara’, sekalipun sebagiannya ada yang oleh syara’ kadangkadang disunnatkan dan ada kalanya dimakruhkan. Sesuatu yang oleh syara’ tidak diberinya pembatasan, mereka dapat menetapkan menurut kemutlakan hukum asal.
Prinsip di atas, sesuai dengan apa yang disebut dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata:
"Kami pernah melakukan ‘azl’, sedang waktu itu al-Quran masih turun; kalau hal tersebut dilarang, niscaya al-Quran akan melarangnya."
Ini menunjukkan, bahwa apa saja yang didiamkan oleh wahyu, bukanlah terlarang. Mereka bebas untuk mengerjakannya, sehingga ada nas yang melarang dan mencegahnya.
Demikianlah salah satu daripada kesempurnaan kecerdasan para sahabat.
Dan dengan ini pula, ditetapkan suatu kaidah, "Soal ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan syariat yang ditetapkan Allah; dan suatu hukum adat tidak boleh diharamkan, kecuali dengan ketentuan yang diharamkan oleh Allah."
Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Ahmad Sarwat, Lc