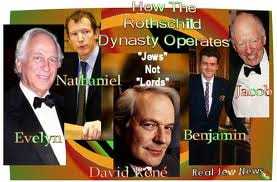Eramuslim.com – Pagi itu, tanggal 2 Syawal, tanggalan Masehi menunjuk pada angka 28 Maret 1830. Sholat Subuh di mushola kecil Pesanggrahan Metesih berjalan seperti biasa. Usai sholat, diisi dengan wirid dan doa, serta wejangan singkat dari Diponegoro sendiri kepada para jamaah. Usai wejangan Diponegoro hendak keluar dari mushola namun dicegat oleh Panglima Muda Basah Gondokusumo.
 “Maaf Kanjeng Pangeran, apakah tidak sebaiknya semua pengiring yang akan ke Wisma Residen pagi ini juga membawa serta senjata mereka? Saya punya firasat kurang enak…”
“Maaf Kanjeng Pangeran, apakah tidak sebaiknya semua pengiring yang akan ke Wisma Residen pagi ini juga membawa serta senjata mereka? Saya punya firasat kurang enak…”
Diponegoro menepuk bahu salah seorang kepercayaannya itu dan tersenyum, “Aku rasa tidak perlu. Ini kunjungan biasa. Silaturahmi biasa saja. Cukuplah Allah sebagai penjaga kita semua. Bismillah… “
Panglima Muda Basah Gondokusumo sebenarnya ingin membantah, namun hal itu diurungkan karena tidak enak hati.
Setelah semua persiapan selesai di pagi hari itu, Diponegoro dan rombongan kecilnya mulai meninggalkan pesanggrahan menuju Wisma Karesidenan Kedu. Seribuan pasukannya diperintahkan untuk menunggu di pesanggrahan.
Pagi itu Diponegoro mengenakan pakaian yang biasa saja, jubah dan sorban putih seperti keseharian. Tidak ada tanda-tanda kebesaran yang dikenakan maupun yang dibawanya. Yang menyertai Diponegoro antara lain Pangeran Diponegoro II, Pangeran Djonet atau Raden Mas Djonet, dan Raden Mas Raib.
Empat orang panglima utamanya juga ikut yaitu: Basah Gondokusumo, Basah Mertonegoro, Basah Suryowinoto, dan Panglima Pasukan Kedu Utara, Basah Imam Musbah. Dua penasihat agamanya, yaitu Haji Ngiso dan Haji Badaruddin, serta dia punakawan setianya, Bantengwareng dan Joyosuroto, juga ikut.
Di sepanjang jalan, rakyat Magelang kembali menyambutnya. Demikian juga para serdadu Belanda yang berbaris rapi di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan tangannya. Semuanya tampak penuh suka cita dan kedamaian.
Di gerbang Wisma Residen Kedu, Diponegoro dan rombongan harus melewati barisan kehormatan serdadu Belanda yang mengapit di kedua sisi jalan. Jenderal De Kock, Kolonel Cochius, dan para pembesar lainnya berdiri menyambut di tangga Wisma. De Kock langsung mengajak Diponegoro memasuki ruang baca di mana telah ada empat buah kursi kayu jati menghadap meja persegi yang juga terbuat dari kayu jati. Sebuah kursi jati lagi berada agak di belakang.
“Silakan duduk Kanjeng Sultan,” ujar De Kock dengan ramah. Diponegoro saat itu memang tidak mau dipanggil lagi dengan sebutan ‘Pangeran Diponegoro’ karena gelar tersebut sudah dianugerahkan kepada salah satu anaknya, Diponegoro II, dan dia ingin disebut sebagai Sultan Ngabdulkamid.
Diponegoro alias Sultan Ngabdulkamid duduk di kursi yang menghadap lurus ke pintu utama. De Kock duduk dan tiga pendampingnya yaitu Residen Valck, Ajudan pribadi Mayor de Stuers, dan Kapten Roeps sebagai penterjemah juga duduk.[ Dalam versi sejarah Diponegoro tulisan Wardiman Djojonegoro (2019), yang duduk di ruangan itu selain Diponegoro dan De Kock adalah: Penerjemah militer Belanda untuk Bahasa Jawa Kapten Johan Jacob Roeps, lalu dua ajudan militer (Mayor De Stuers dan Letkol Roest. Residen Kedu Vlack tidak disebut disini. ]