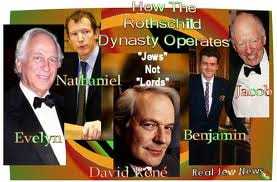Pada bagian pertama tulisan ini dijelaskan bagaimana supremasi laki-laki dalam Gereka Katolik telah banyak menimbulkan skandal memalukan citra gereja sendiri dan bagaimana Gereja Katolik memarginalkan kaum perempuan. Terjadi jurang yang makin dalam antara fungsi dan prinsip-prinsip gereja. Meski faktanya, kaum perempuan yang lebih banyak memberikan kontribusinya bagi keberlangsungan gereja.
Di AS, 60 persen peserta misa di gereja adalah kaum perempuan. Mereka juga pemberi dana sumbangan terbesar bagi gereja, sekitar 6 miliar setiap tahunnya. Tapi kehadiran kaum perempuan dalam struktur institusi gereja tetap nihil. Vatikan, sebagai institusi wakil penganut Katolik sedunia, tidak pernah memperhitungkan seorang perempuan untuk mendapatkan jabatan atau posisi tinggi di gereja. Kalaupun ada, mereka hanya ditempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas manajemen dalam keuskupan, dan itupun jumlahnya tidak banyak. Saat ini, jumlah biarawati jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pendeta. Tapi ketika sebagian dari mereka ikut angkat suara-misalnya dalam isu reformasi jaminan kesehatan di AS baru-baru-eksitensi mereka tetap dianggap sebagai angin lalu.
Delapan tahun setelah Skandal Bolton, Kathleen McChesney, mantan FBI yang ikut dalam tim studi masalah pelecehan seksual di keuskupan-keuskupan di AS mengatakan, “Kaum lelakilah yang harus mendengarkan diri mereka sendiri. Sepengetahuan saya, tidak ada perempuan di Vatikan yang terlibat dalam isu-isu pelecehan seksual.”
Bulan Maret lalu, Direktur Eksekutif National Leadership Roundtable-sebuah wadah perkumpuan para pengusaha di AS-Kerry Robinson dan beberapa kolega perempuannya terbang ke Roma untuk mendesak para kardinal agar perempuan lebih banyak dilibatkan dalam gereja. Robinson frustasi melihat kurang dibukanya kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam kepemimpinan gereja, akibatnya, gereja jadi makin kurang relevan bagi kaum perempuan dan bagi anak-anak mereka.
“Ini adalah hal yang penting, bagaimana orang memandang kehidupan gereja. Sekarang, gereja dipandang sebagai dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum lelaki, ditutup-tutupi oleh kaum lelaki dan dibiarkan berlarut-larut oleh mereka. Untuk mengatasi ini semua, gereja harus mengikutsertakan lebih banyak kaum perempuan,” tukas Robinson.
Tentu saja, kaum perempuan bukan obat penyembuh semua penyakit. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuasaan juga bisa sangat egois dan kejam seperti layaknya kaum lelaki. Dan kehadiran perempuan, tentu saja tidak menjamin sebuah organisasi bebas akan tindak kriminal dan korupsi. Dalam hal ini, tanyakan saja pada Lynndie England, perempuan ini tersenyum ke arah kamera saat ia melecehkan para tahanan di kamp penjara Abu Ghraib. Di sisi lain, sulit membuktikan bahwa Gereja Katolik yang didominasi kaum lelaki menciptakan “surga” bagi para pemangsa seks; dan masih masih banyak pendeta-pendeta yang baik di dunia, yang setia dengan keimanannya. Para peneliti meyakini, sebenarnya tingkat penyimpangan di dalam gereja bisa dibandingkan dengan tingkat penyimpangan di institusi lain, seperti organisasi kepemudaan, sekolah dan dalam keluarga. Pelecehan n seks relatif tinggi dan mengerikan.
“Survei-survei mengindikasikan bahwa satu dari tiga gadis remaja dibawah usia 18 tahun, mengalami pendekatan pelecehan seksual yang tidak mereka inginkan dari orang dewasa. Dan di kalangan remaja laki-laki, satu dari lima orang diantara mereka, mengalami hal serupa,” ungkap Margaret Leland Smith, peneliti bidang hukum dan kriminal di John Jay College yang menganais data dari kasus-kasus pelecehan seksual di AS.
Meski demikian, tak terbantahkan bahwa hierarki Gereja Katolik yang lebih mengendepankan kaum lelaki, sangat lambat merespon krisis yang terjadi di balik dinding gereja-bahkan setelah terungkapnya kasus pelecehan seksual dan penganiyaan juga terjadi di AS-dan masih lebih melindungi kepentingan gereja sendiri dibandingkan melindungi anak-anak asuhan gereja.
“Gereja Katolik seharusnya bisa menarik orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kapan saja mereka inginkan, atau memecat orang-orang itu,” kata Pendeta Marie M. Fortune dari Persatuan Gereka Kristus dan pendiri FaithTrust Institute, sebuah organisasi untuk menghentikan tindak kekerasan seksual.
“Anda bisa melontarkan argumen yang baik dengan mengatakan bahwa masalah ini muncul karena persoalan hierarki dalam sebuah institusi ‘klub para lelaki’, sebuah institusi yang sangat konservatif dan tidak tersentuh oleh masyarakat,” sambung Pendeta Fortune.
Berbagai studi menunjukkan hal-hal yang secara intuisi sudah menjadi rahasia publik; tanpa harus mempertanyakan lagi bahwa sekelompok lelaki picik melakukan tindakan yang buruk. Profesor bidang sejarah dan penulis buku The Company He Keeps: A History of White College Fraternities, Nicolas Syrett mengatakan, studi-studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa 70 sampai 90 persen genk pelaku pemerkosan di kampus-kampus, adalah para lelaki dalam kelompok persekutuan. Syrret, tentu saja menarik perbedaan yang tegas antara hierarki di Gereja Katolik dengan kelompok persekutuan para lelaki di kampus-kampus. Kelompok persekutuan didorong untuk melakukan hubungan seks dengan banyak perempuan, sedangkan para pendeta tidak demikian. Tapi dalam dua kasus itu ada kesamaan bahwa “kaum lelaki didorong untuk memiliki keyakinan bahwa mereka punya kekuasaan untuk melakukan tindakan itu.”
“Saya sangat meyakini, jika hierarki Gereja Katolik mendisplinkan orang-orang seperti itu hanya karena khawawatir akan -reputasi gereja, orang-orang ini akan menciptakan ruang dimana akan muncul keyakinan bahwa menyiksa dan melakukan pelecehan seksual pada anak-anak akan adalah hal yang biasa,” sambung Syrret.
Richard Sipe, mantan pendeta yang selama tiga dekade ini meneliti ajaran gereja tentang seks dan dampaknya pada perilaku para pendetanya, setuju dengan pendapat Syrret. “Kependetaan adalah sebuah kelompok yang dalam pikirannya tertanam bahwa mereka punya hak-hak istimewa. Pikirkanlah hal ini. Budaya lain apa yang Anda ketahui yang semuanya didominasi kaum lelaki, baik secara praktek maupun secara teori,” tandas Sipe.
Yesus memang tidak mengajarkan apapun tentang peran yang harus dimainkan kaum perempuan di gereja di masa depan. Sebagai pemimpin gerakan kecil dan radikal, Yesus mengajak semua orang untuk menjadi pengikutnya, termasuk perempuan bersuami, perempuan yang belum menikah, para pelacur dan ayat-ayat Injil memberikan peran khusus bagi kaum perempuan. Dalam Injil disebutkan, kaum perempuan-lah yang pertama kali melihat dibangkitkannya Yesus dan melaporkan kejadian itu pada kaum lelaki.
Diduga, pada masa awal gereja, kaum perempuan diberi kesempatan berkiprah di gereja. Dalam suratnya pada penguasa Roma, sahabat Yesus, Paul menyebutkan beberapa nama perempuan yang berperan di gereja, antara lain; Phoebe, Prisca, Tryphena dan Tryphosa. Ia bahkan menyebut adanya “rasul” perempuan bernama Junia. Fakta ini mengguncang gereja dari generasi ke generasi yang berpikir bahwa seorang seorang “rasul” haruslah seorang laki-laki.
Menurut penulis buku yang baru terbit berjudul “Christianity: The First Theree Years”, Diarmaid MacCulloch, sosok Junia seringkali mengubah namanya dengan nama laki-laki. “Anda bisa merasakan, bahwa masa awal gereja sudah menjauhkan sosok perempuan yang memiliki kekuasaan di gereja,” ujar MacCulloch.
Fakta ini membuktikan kesalahan klaim yang menyebutkan bahwa masa-masa awal kekristenan merupakan masa kejayaan kaum perempuan. Perempuan, umumnya, diposisikan sebagai mahkluk yang rendah dan bahwa lelaki Kristen yang baiklah yang berhak mengendalikan gereja. Meski faktanya para pendeta bahwa Paus juga menikah, kaum perempuan yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan gairah seksual, dalam dunia lelaki Kristen, perempuan itu dianggap sebagai seperti Hawa yang bersekongkol dengan setan untuk menggoda Adam. Para Kristen Katolik menginginkan kaum perempuan meniru Maria, si perawan suci agar perempuan menemukan kekuatan dan kemerdekaannya. (bersambung)