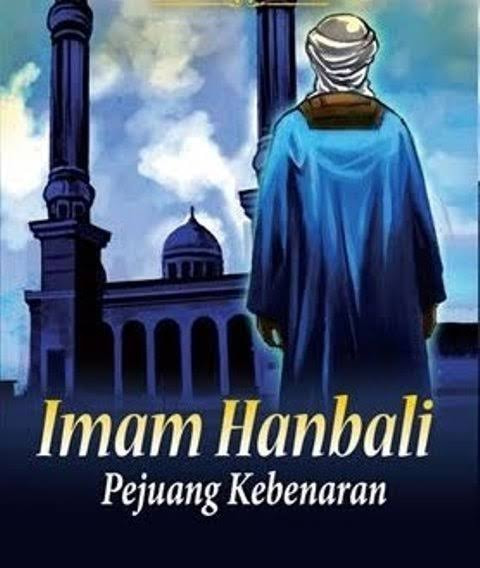Oleh: Bambang Prayitno
Oleh: Bambang Prayitno
Pendaras Pengetahuan
SEPENGGAL Maret, 88 tahun yang lalu
Jiwa Hafiz Abdul Hamid dirasuki gelora yang tak padam-padam. Tapi ia susah mendefinisikan perasaannya. Mungkin sedikit saja yang bisa ia mengerti. Gelora yang ia rasakan itu; semacam semangat yang menyala dengan haru yang terus menyelubunginya. Atau semacam energi paling murni dari jiwanya yang terus mencari tempat untuk ia alirkan
Ia tak tahan untuk mengungkapkan perasaan itu kepada karibnya. Kasak-kusuk dan perbincangan penuh rasa penasaran yang menjalar pada semua orang yang hadir di warung kopi langganannya selama berhari-hari sejak berbulan lalu, terus mengusik kepalanya. Dan ia tak tahan dilanda gelora yang membuatnya terjaga pada sepertiga malam setiap harinya
Beberapa pekan berlalu setelah lebaran Idul Fitri tahun itu, Hafiz akhirnya mantap mengumpulkan keberaniannya. Ia, lelaki kurus yang hanya tukang kayu biasa itu, lalu mengajak lima sahabat karibnya yang biasa ia temui di warung kopi, untuk membicarakan dan mendengarkan perasaannya. Mendengarkan gundah sedu jiwanya
Kelima sahabat yang ia ajak bertemu itu; Ahmad Al-Hushor, seorang tukang cukur yang sederhana; Fuad Ibrahim, tukang penggosok pakaian yang memiliki langganan tak seberapa; Ismail Izz, penjaga kebun dari seorang tuan tanah di Ismaili; Abdurrahman Hasbullah, seorang sopir; dan Zaki Al-Maghribi, pemilik rental dan bengkel sepeda, semuanya menyanggupi untuk meluangkan waktu dan bertemu Hafiz