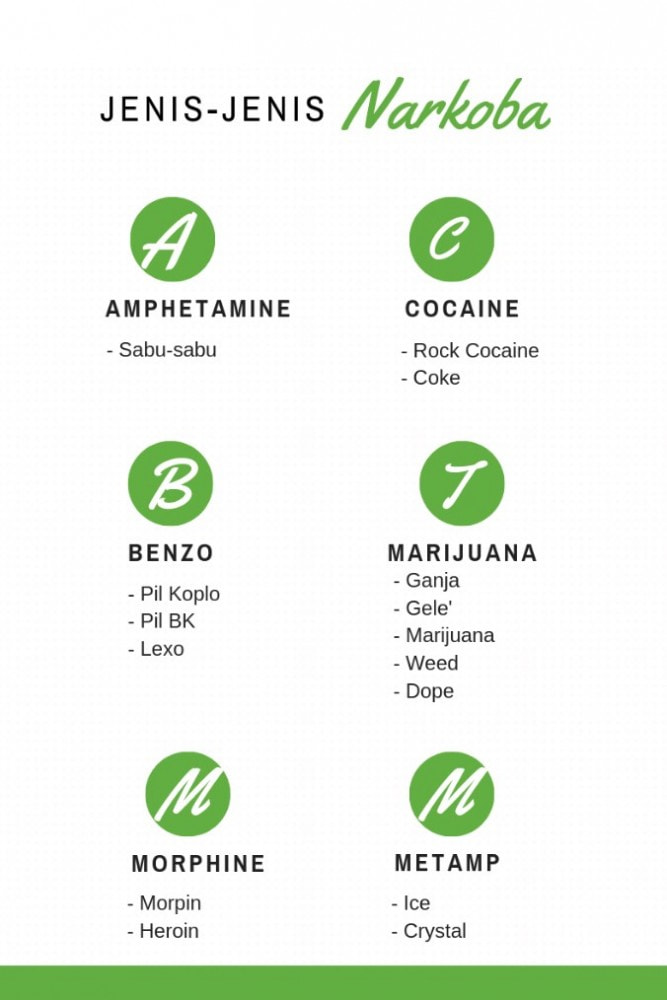Assalammu’alaikum wr. wb.
Ibu Anita, saya pria berumur 30 tahun. Belum lama ini saya mengalami peristiwa yang mengguncang hidup saya. Saya mengalami perceraian setelah menikah selama 3 tahun, dan sudah memiliki putra berumur hampir 2 tahun. Mantan istri saya berumur 30 tahun. Selama pernikahan, rumah tangga saya selalu diwarnai pertikaian. Hal ini disebabkan perbedaan pemikiran yang saling bertolak belakang. Dia sebenarnya banyak tahu hukum agama, tapi lebih banyak mencari keringanan- keringanan yang tidak pada tempatnya.
Saya dicap terlalu agamis dan ekstrem dalam menjalankan agama, padahal menurut saya sebenarnya kadar keimanan saya masih sangat jauh dari sempurna. Apabila saya menjalankan ibadah sholat, saya dianggap menelantarkan anak kami yang menurutnya harus selalu diawasi dan dijaga. Padahal kami tinggal bukan seorang diri, melainkan bersama orang tuanya sehingga di rumah tersebut ramai orang. Saya dianggap kurang bertanggung jawab karena lebih mementingkan ibadah dibanding dengan keluarga, walaupun itu ibadah fardlu.
Selama masa perkawinan dengannya, saya lebih banyak diam, berusaha sabar dan menuruti kemauannya karena ingin menghindari keributan yang lebih besar. Di samping itu juga karena saya merasa tidak punya kuasa apapun terhadap mantan istri saya, karena saat itu kondisinya adalah kita masih menumpang di rumah orang tuanya di kota X, dan saya di bekerja di kota Y disebabkan mantan istri saya masih takut hidup kekurangan dan takut mandiri bila ikut dengan saya di kota Y, Selain dia juga masih sayang untuk meninggalkan pekerjaannya di sebuah hotel, yang dilingkari dengan kemewahan sehingga membuatnya lebih sering melihat ke atas.
Saya merasa tidak punya power sebagai pemimpin keluarga saat berada di rumah orang tuanya, karena saya tidak mampu membimbing dan membuatnya patuh pada suami selama dia masih bersikukuh tetap tinggal di rumah orang tuanya. Dia masih sering berlindung di balik orang tuanya. Bahkan nama pemberian saya untuk anak kami yang Insya Allah bermakna baik pun tidak dipakai sehari-hari, yang dipakai adalah nama panggilan yang diberikannya yang tidak ada unsur mendoakan, sehingga nama asli anak saya pun tenggelam. Saat itu seringkali saya berpikiran mungkin lebih baik kami bercerai saja, karena saya merasa amat berat tanggung jawab yang harus saya pikul dengan beristrikan dia, saya tidak mampu lagi memikirkan cara apa lagi yang harus saya pakai untuk membinanya dan membuatnya patuh.
Dari cara halus berupa ajakan dan perkataan lembut sampai kasar dengan marah-marah. Bahkan saya sering melontarkan ancaman ke dia, seperti apabila keadaan seperti terus dan dia tidak mau disuruh menghormati saya sebagai pemimpin keluarga, maka saya tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini. Bila saya berkata seperti itu dia pun langsung terdiam. Saya sadar bahwa sebenarnya kita masih saling mencintai, tapi perilakunya sering tidak mencerminkan itu. Apalagi bila mengingat kondisi kami yang sudah mempunyai seorang putra, saya berusaha meredam nafsu untuk menceraikannya. Namun kejadian perceraian itu akhirnya tidak bisa dihindari, saat itu saya sudah pindah bekerja di negara Z, sedangkan dia masih di kota X.
Hanya karena masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik dan saling menekan harga diri masing-masing, bom waktu yang saya pendam pun akhirnya meledak juga di saat saya mengunjunginya di rumah orang tuanya. Saya mengembalikan dia ke orang tuanya. Tapi akhirnya kami berdua menyesali keputusan saya tersebut. Apalagi mengingat kami sudah mempunyai anak, saya takut anak kami akan banyak dirugikan, walaupun dia tinggal dengan kakek dan neneknya. Walaupun saya tahu, mereka memang menyayangi cucunya, bahkan menurut saya melampaui batas cara menyayanginya. Saya berusaha introspeksi ke diri sendiri, bahwa mungkin saya kurang sabar dalam mendidik mantan istri saya tersebut. Dan akhirnya kami pun berniat untuk rujuk kembali.
Dia pun bersedia untuk ikut dengan saya ke negara Z meninggalkan pekerjaan dan dunianya membawa anak kami. Tapi saat keputusan final untuk rujuk sudah di depan mata, saat persiapan sudah dilakukan untuk meminta dia kembali dari orang tuanya dan menjemput dia beserta anak kami, dia memunculkan satu isu yang sangat mengganggu saya dan membuat saya jengkel. Dia ingin agar saya menanda tangani surat perjanjian rujuk di atas segel, yang menyatakan bahwa saya akan menyayangi dia dan anak kami, dan apabila saat dia sudah pindah bersama saya dan meninggalkan pekerjaan dan dunianya, bila akhirnya pun saya menalak dia lagi, saya diminta rela memberikan nafkah sebesar 1/3 gaji saya, pembagian harta gono gini yang adil, dan anak kami tetap ikut dengannya selama belum bisa memilih.
Semua perjanjian tersebut gugur apabila dia yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dia secara khusus adalah hanya perselingkuhan, padahal tidak pernah saya mengkhianati pernikahan kami, alasan saya menceraikan dia adalah karena saya merasa tidak mampu lagi menjadi pemimpin baginya. Saya menghadapi dilema di sini. Satu sisi saya ingin membesarkan anak saya dan mendidik mantan istri saya lagi agar lebih dekat dengan Allah, di lain sisi kalau saya menerima persyaratannya, saya khawatir saya mengadakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ada, dan mengharamkan yang sudah dihalalkan Allah.
Syarat 2 dan 3 bagi saya tidak ada masalah. Tapi syarat yang pertama, bukankah tidak semestinya dia meminta seperti itu? Dan juga saya takut perjanjian ini hanya akan kembali melemahkan posisi saya sebagai suami, sehingga tidak bisa membinanya, dan tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia berbuat seenaknya. Mungkin perjanjian itu dijadikan jaminan untuknya agar saya tidak lagi semena-mena menalaknya lagi, tapi keputusan saya ingin rujuk lagi dengannya bukan untuk menalaknya dan menyengsarakan dia dan anak kami. Saya sangat berharap ibu dapat membantu saya mencari jalan keluar permasalahan saya ini. Jazakallah,
Wassalam,
Wassalammu’alaikum wr. wb.
Saudara Abd yang dimuliakan Allah SWT, nampaknya tidak mudah ya kehidupan rumah tangga yang bapak jalani. Baru tiga tahun berjalan sudah demikian banyak konflik yang dialami sampai hampir berujung pada perceraian. Mendidik dan membina pasangan kita memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu banyak energi serta kesabaran yang harus dipersiapkan jika terdapat banyak perbedaan yang harus disesuaikan. Nampaknya memang dibutuhkan waktu lebih untuk dapat membuat rumah tangga terbentuk sesuai harapan bapak.
Perbedaan pemahaman dalam menyikapi kehidupan religius yang hendak dijalani terkadang juga menjadi kendala untuk membentuk keluarga sakinah. Oleh karenanya dibutuhkan proses yang harus disikapi dengan pengertian serta kesabaran sehingga pasangan kita dapat melangkah seiring dengan langkah kaki kita. Dan kata-kata memang tidak semudah praktek yang harus dijalani, terlebih dalam membimbing wanita dibutuhkan kepekaan dari seorang suami untuk bisa menyelami jiwanya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda agar berhati-hati dalam mengarahkan wanita karena ibarat ranting mudah bengkok namun jika terlalu keras bisa mematahkannya.
Kelihatannya salah satu kendala bapak dalam membimbing istri adalah masih tinggal satu atap dengan mertua, dengan memisahkan diri dan pergi ke negara Z merupakan langkah yang cukup baik. Karena diharapkan kemandirian akan lebih memudahkan kerjasama yang terjalin antara bapak dan istri. Terlebih istri saat ini mulai lebih mengalah dengan meninggalkan pekerjaannya dan mau ikut pindah tinggal bersama bapak. Namun nampaknya trauma perpisahan yang pernah terjadi masih dirasakan oleh istri. Yaitu ia khawatir jika setelah ia meninggalkan pekerjaannya maka bapak bisa bertindak sewenang-wenang dengan mentalaknya begitu saja di saat ia tak punya tempat bergantung selain bapak. Meskipun saya yakin bapak sama sekali tidak punya niat untuk mentelantarkannya.
Menurut saya, kekhawatiran istri bapak merupakan hal yang wajar saja dirasakan oleh seorang wanita yang cemas karena pernah hampir ditalak sebelumnya. Dan itu memang hak wanita dalam Islam yang sah-sah saja digunakan. Menurut saya ini justru menunjukkan keadilan Islam, sebagaimana Islam memberikan hak kepada suami untuk mentalak, maka istripun diberi kesempatan untuk melindungi dirinya dengan mengajukan syarat untuk rujuk. Namun, memang isi dari perjanjian tersebut tidak boleh menyalahi hukum islam yang lain atau terkait dengan kemaksiatan.
Misalnya mengenai hak atas 1/3 gaji, jika hak asuh anak jatuh pada ibunya, maka bapak memang wajib untuk tetap memberikan uang kepada mantan istri untuk dapat merawat dengan baik anak bapak. Namun mengenai harta gono-gini mungkin perlu diklarifikasi, karena dalam islam tidak ada pembagian harta sama rata setelah bercerai. Namun yang benar adalah harta suami menjadi hak suami dan harta istri menjadi hak istri setelah mereka bercerai dan bukannya membagi lagi harta itu setelah perceraian dengan jumlah yang sama.Untuk urusan persyaratan ini nampaknya bapak memang perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan ustadz yang memahami syariat Islam.
Jika bapak mengkhawatirkan bahwa pengajuan syarat ini akan menyulitkan bapak dalam membina, seharusnya tidak demikian. Artinya disadari atau tidak berarti bapak menggunakan hak talak sebagai senjata untuk mengarahkan istri. Menurut saya proses pembinaan yang demikian kurang tepat karena menggunakan ancaman sebagai cara menjaga kepatuhan, tapi akan jauh lebih baik jika proses itu dilakukan dengan membawa kesadaran pasangan sehingga sukarela untuk berubah. Namun segalanya memang akan kembali kepada bapak yang akan membentuk dan membina keluarga sendiri. Apa yang tertulis hanya sekedar membuka wawasan sehingga dapat melihat sudut pandang yang berbeda. Saya turut mendoakan semoga bapak sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah S.W.T. Wallahu’alambishawab.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.