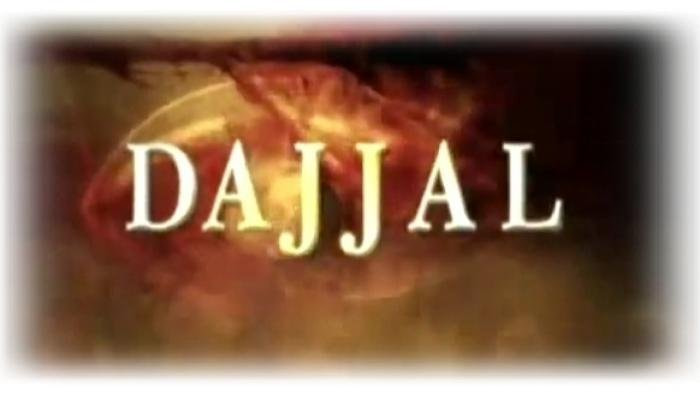Ia yang kecil fisiknya itu, ternyata memiliki sensitifitas nan menjulang. Dijawablah tanya itu, tanpa sedikit pun canggung, “Aku menyesal, Bang.” Seperti siapkan jawab, lelaki dewasa itu langsung mencegat dengan tanya selanjutnya, “Mengapa? Memang, apa dosamu?”
Tumpahlah lagi bulir bening dari mata nan cerah itu. Hingga keduanya terhenti dari tanya-jawab itu. Sekeliling seakan sepakat. Berhenti. Putaran waktu semakin tak terasa lantaran hening antara kedua insan itu.
“Tadi,” mulai si kecil mengisahkan, “aku memohon kepada Allah agar Dia hidupkan lagi ibuku.” Alis lelaki dewasa terangkat dengan sedikit kerutan dahi. Ia menodong, “Ah, mustahil itu terjadi. Memang kenapa kau meminta hal mustahil itu?” Si kecil melanjutkan, “Aku anak yang nakal, Bang. Aku durhaka. Tak pernah mendengar perintah ibu,” ungkapnya terbuka, apa adanya. “Kini, sesalku memuncak. Ibuku telah dipanggil Allah. Aku ditinggalnya sebatang kara,” pungkas anak itu.
Berniat empati, lelaki dewasa itu tak ucap sepatah kata pun. Didekaplah sang anak, bagai adiknya sendiri. Keduanya larut dalam perenungan dan pikiran masing-masing.
Duhai diri, mengertilah. Begitulah sesal mendatangi. Selalu di akhir. Mustahil ia datang di muka. Maka, perbaiki dirilah sebelum semuanya berakhir. Perbaiki diri, agar sesalmu tak terbit kemudian. Sebagaimana dialami anak itu, sebesar apa pun sesalnya, sederas apa jua tangisnya, sekeras dan setulus pintanya, sang ibu yang telah wafat, amatlah mustahil untuk kembali. [Pirman/kisahikmah]