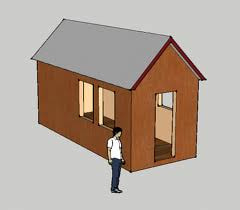Teman hidup adalah teman yang senantiasa menjadikan hidup lebih hidup. Ia seperti bahan bakar buat nyala api pada sebuah lampu. Cahayanya akan terus menerangi gelapnya malam. Terus dan selalu terus, selama bahan bakar tetap bersisa.
Seperti itulah, kira-kira, idealnya suami isteri. Seperti Khadijah binti Khuwailid yang menenteramkan hati Rasulullah saw. ketika pertama kali bertemu Jibril. Seperti Hajar yang mengokohkan hati Ibrahim a.s. ketika harus meninggalkan isteri dan bayinya di bukit tandus tak berpenghuni karena perintah Allah. Juga, seperti Rasulullah yang menyejukkan hati Aisyah ketika fitnah besar memburunya.
Nikmatnya berpasangan hidup seperti itu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah menjadi tempat yang paling menyenangkan sekaligus menyehatkan. Seperti halnya bengkel, mesin-mesin diri yang semula nyaris rusak tiba-tiba seperti baru setelah keluar dari sana. Karena di tempat itulah suami isteri bisa saling menenteramkan dan menyegarkan.
Begitulah mungkin angan-angan Bu Rara. Ibu satu anak ini merasakan ada sesuatu yang lain dalam bahtera rumah tangganya. Lain, karena ia merasa kurang terbuka dengan suaminya. Begitu pun yang ia tangkap tentang suaminya. Suaminya agak kaku kalau cerita tentang banyak hal. Soal pribadi, pekerjaan, anak-anak, dan aktivitas lain.
Entah apa yang salah. Rasa-rasanya semua rutinitas rumah tangga berjalan lancar-lancar saja. Hubungan suami isteri tak ada masalah. Ekonomi keluarga lumayan cukup. Anak juga sehat dan menggemaskan. Semuanya biasa. Tak ada masalah. Cuma, yang tadi itu. Ia kok agak canggung dengan suaminya.
Beda betul kalau dibandingkan dengan keluarga teman-temannya. Bisa ngobrol sambil berjalan santai. Kemana-mana selalu berdua. Nggak canggung kalau bercanda. Senyum mereka begitu lepas. Tanpa dibuat-buat.
Pernah temannya nanya ke Rara. “Kamu kok kalau jalan berdua saling cuek. Seperti belum nikah aja. Kikuk, gitu,” ucap sang teman suatu kali. Pertanyaan itu seolah mengkritik Rara yang terlalu kaku mengamalkan ajaran Islam. Tapi, buat Rara lain. Ia bukan nggak ingin luwes dengan suami. Tapi, nggak bisa.
Buat ukuran normal, dua tahun pernikahan bukan waktu yang sebentar. Teramat cukup buat saling mengenal, memahami, dan tentu saja mencintai. Memang sih, Rara mengakui kalau perkenalannya dengan suami hanya dua minggu sebelum pernikahan. Sebelumnya, “Boro-boro kenal, ketemu aja belum pernah.” Begitulah komentar Rara ketika adiknya nanya-nanya soal calon suaminya waktu itu.
Buat Rara, justru itulah kebanggaan dirinya. Ia ingin buktikan kepada bapak ibu dan adik-adiknya kalau pernikahan bisa berlangsung tanpa proses pacaran. Yang penting, sama-sama punya niat ikhlas karena Allah. Ikhlas demi melahirkan generasi Islam pilihan. Itu saja.
Tapi, kok sekarang seperti ada yang nggak beres. Apa, ya? Rara bukan tidak mau membicarakan itu ke suami. Berkali-kali ia coba. Tapi, selalu saja mandeg ketika sudah saling bertatapan. Semua kata-kata yang sudah disiapkan lenyap. Yang keluar cuma kalimat, “Mau minum, Mas?”
Ibu yang semasa gadisnya terkenal sebagai aktivis masjid ini mencoba melihat ke belakang. Menoleh apa yang salah pada dirinya. Bisa-bisa saja ia menyalahkan suami. Tapi, masalah nggak pernah selesai kalau cuma bisa saling menyalahkan.
“Ada banyak sebab,” ucap Bu Rara membatin. Ia seperti mengingat-ingat sesuatu. Semasa gadis, ia memang nyaris tak pernah ngobrol sama laki-laki kecuali bapak. Semua adiknya perempuan. Dan ia anak sulung. Di kampus lebih ketat lagi. Ia seperti tak peduli dengan dunia laki-laki. Ruang kampus bagi Rara cuma tiga: kelas, masjid, dan perpustakaan. Ia benar-benar kuper soal laki-laki.
Itulah mungkin kenapa ada rasa takut saat Rara diperkenalkan calon suami. Rara masih ingat betul momen itu. Jantungnya berdetak kencang. Peluh keringatnya bercucuran. Ucapannya terbata-bata seperti orang gagap. Bingung, grogi, takut, malu jadi satu dalam hati Rara. Jangankan bicara luwes, melihat calon suami saja nggak berani. Ia cuma berani menjadi pendengar setia.
Anehnya, rasa-rasa nggak enak itu masih melekat. Semula Rara yakin itu masih adaptasi. Tapi, kok lambat amat. Entah kenapa, ia merasa nyaman kalau sendiri. Dan, tiba-tiba kikuk kalau suami pulang dari kantor. Seolah, ada orang asing yang akan masuk rumahnya. Kalau bukan karena sadar bahwa ia sudah bersuami isteri, mungkin Rara sudah kabur dari rumah. Astaghfirullah!
Seperti itulah suasana awal adaptasinya dengan suami. Betapa Rara ingin seperti isteri-isteri lain yang begitu hangat terhadap suami. Senyum, sapaan, dan lain-lain. Sepertinya tak ada cara lain buat dirinya. “Ya, mungkin saya mesti mengikis kekhawatiran masa lalu. Harus,” tegas Rara tersadar.
Ada satu lagi yang mungkin jadi sebab. Dan itu datang dari suami Rara. Rara khawatir sekali kalau dugaannya itu memang benar. Memang, ada kesenjangan status pendidikan antara Rara dan suaminya. Ia sarjana, sementara suaminya cuma sampai di tingkat tiga fakultas ekonomi. Dan ini sempat jadi bahan penolakan orang tua Rara ketika proses lamaran. Syukurnya, Rara mampu menjelaskan ke orang tua.
Buat Rara, beda pendidikan bukan jadi masalah. Yang penting suaminya seorang aktivis Islam. Itu saja. Tapi, entahlah. Rara masih ragu kalau suaminya sudah tak masalah dengan soal itu. Pasalnya, kata-kata orang tuanya saat lamaran dulu memang cukup telak. “Apa anak tidak menganggap masalah menikah dengan wanita yang pendidikannya lebih tinggi?” ucap bapak Rara waktu itu.
Rara yakin suaminya bukan orang cengeng. Tapi, ia lagi-lagi bingung mengolah keadaan. Paling tidak, ia bisa tunjukkan kalau soal beda titel tak masalah. Dari dua kemungkinan sebab itu, Rara masih menakar-nakar mana yang lebih dominan. Pada titik ini, Rara ingin memulai apa yang bisa ia lakukan. Dan masalah itu ada dalam dirinya sendiri. “Gimana mungkin mengharapkan perubahan dari suami, kalau diri sendiri belum berubah,” tekad Rara pada dirinya sendiri.
Nikmatnya hidup didampingi teman. Teman yang bukan hanya mampu menjaga dan melindungi. Tapi, juga mampu menampilkan diri apa adanya. Sebagaimana nyala lampu yang tak pernah pura-pura. ([email protected])