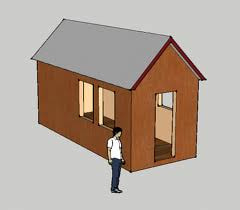Cemburu dalam ruang-ruang keluarga kadang mirip seperti mecin dalam masakan. Tanpa mecin, masakan jadi hambar. Begitu pun sebaliknya. Kebanyakan mecin, masakan jadi sangat tidak sehat.
Cemburu merupakan hal lumrah dalam hubungan cinta. Bahkan, sangat bagus. Dalam Islam, seorang bisa dipertanyakan keislamannya jika tak lagi cemburu jika Islam dicela, dipermainkan, dan dikucilkan. Semakin tinggi kecintaan seorang muslim dengan agamanya, kian tinggi tingkat kecemburuannya. Bahkan Allah swt. Yang Maha Sayang, cemburu jika ada hambaNya melakukan dosa. Bedanya, cemburu Allah tidak karena emosi.
Begitu pun soal interaksi suami isteri. Islam mencela seorang suami atau isteri yang cuek dengan pasangannya. Tak peduli mau gonta-ganti pasangan, yang penting bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Sikap ini disebut sebagai dayus, orang yang cemburunya telah mati.
Masalahnya, seperti apa takaran cemburu yang wajar. Karena dalam rumus keseimbangan hidup: yang kurangnya bisa buruk, kalau kebanyakan juga dapat merusak. Paling tidak, bisa merusak keseimbangan emosi diri sendiri. Setidaknya, dilema itulah yang kini dirasakan Pak Endi.
Bapak dua anak ini sebenarnya cukup bahagia. Bukan sekadar anugerah dua balita yang lucu dan sehat, tapi juga isteri yang salehah, cantik, dan punya penghasilan tetap. Walau tak terlalu besar, gaji isterinya bisa menutup kebutuhan rutin keluarga: kontrak rumah, tambahan belanja dapur, bahkan modal usaha. Kadang, bisa menabung buat masa depan sekolah si sulung yang kini duduk di TK.
Dari sudut pandang itu, Pak Endi memang tak ada masalah. Ia patut bersyukur. Tapi, ada kegelisahan lain dari Pak Endi. Pasalnya, tetangga sebelahnya berkantor dekat dengan tempat kerja isteri Pak Endi. Bukankah itu bagus, bisa jalan bareng? Memang. Tapi, tetangganya itu pria, lumayan ganteng, masih lajang lagi. Kalau dibanding dirinya, penampilan tetangganya itu satu banding lima. Artinya, nilai satu buat Pak Endi, dan lima buat si tetangga. Selain itu, sang tetangga begitu ramah, murah senyum, dan supel.
Pak Endi memang yakin, isterinya tidak akan macam-macam. Gimana mungkin mantan aktivis rohis sewaktu di kampus dulu bisa main serong. Naudzubillah min dzalik. Pak Endi yakin itu tak mungkin. Tapi masalahnya, apa tetangganya juga seperti itu.
Tiap kali isterinya berangkat kantor, Pak Endi selalu was-was. Karena jam berangkat isterinya bersamaan dengan si tetangga. Bayang-bayang buruk berkecamuk di kepala Pak Endi tiap melepas kepergian isteri tercintanya. Jalan kaki hampir bersamaan, naik mikrolet dengan nomor yang sama, turun juga di halte yang sama. Begitu pun ketika pulang. Iramanya hampir sama dengan ketika pergi. Gimana kalau mikrolet yang mereka naiki cuma lowong buat dua penumpang. Kalau yang lowong berseberangan, bukankah mereka akan duduk berhadap-hadapan. Saling pandang, senyum, dan sapa. Lebih parah lagi yang lowong sejajar. Bukankah mereka akan duduk bersebelahan. Dan itu pasti akan bersentuhan badan. Setidaknya, tangan mereka.
Pak Endi galau. Ia pandangi isterinya yang berlalu sambil melambaikan tangan. "Assalamu’alaikum, Kak!" suara sang isteri diiringi senyumnya yang manis.
Saat penantian di toko, Pak Endi nyaris tak bisa memikirkan yang lain kecuali isterinya. "Ini nggak bisa dibiarkan terus," gumam batinnya seketika. Tapi gimana? Terus terang, ia agak sungkan bicara terus terang soal ini. Pak Endi khawatir, isterinya bisa salah paham. Dan kalau sudah begitu, masalah bisa tambah runyam.
Mau nyuruh naik taksi, terlalu boros. Bisa-bisa, separuh gaji isteri cuma habis buat taksi. Mau diantar, dengan kendaraan apa? Pasalnya, Pak Endi belum bisa naik sepeda motor. Kenapa nggak belajar?
Itulah repotnya. Pak Endi punya trauma sama motor. Ketika SMA dulu, ia pernah kecebur selokan gara-gara motor yang ia boncengi menabrak tiang listrik. Wajahnya babak belur. Tangan kirinya nyaris patah. Sejak itu, ia jadi kurang akrab dengan sepeda motor.
Kenapa nggak pindah kerja? Sepertinya, Pak Endi mesti mikir ulang kalau meminta isterinya pindah kerja. Soalnya, posisi kerja isterinya lumayan pas dengan kemampuannya di bidang keuangan. Selain itu, suasana ruang kerja pun lumayan baik. Tidak campur antar pegawai. Masing-masing punya pemisah ruang.
Kalau pindah rumah? Pak Endi seperti bertemu titik terang. "Yah, ini mungkin yang paling pas. Toh, si sulung sudah hampir lulus TK," ujar Pak Endi membatin. Ia yakin, isterinya akan terima. Alasan yang paling kuat, demi mendekati sekolah dasar buat anaknya.
Benar saja. Isteri Pak Endi akhirnya setuju. Dengan gerak cepat, ia mencari rumah baru di sekitar lokasi calon sekolah anaknya. Biar mahal sedikit, yang penting bisa menenangkan hati. Soal toko buku? "Insya Allah, bisa diurus belakangan!" tekad Pak Endi mantap.
Di rumah yang ukuran dan bentuknya yang tak jauh beda dengan yang lama, Pak Endi bisa lebih tenang. Walau mesti jalan kaki sepuluh menit, isteri Pak Endi menerima dengan lapang dada. Dan yang paling penting, Pak Endi tak lagi galau ketika isterinya berangkat kerja. Sejak pindahan itu, ia bahkan lebih sering berangkat lebih dulu dari isterinya karena mengantar anak yang beberapa hari lagi lulus di TK.
Beberapa hari berlalu. Di hari Minggu ketika isterinya sedang ke pasar, seorang pemuda memberi salam. "Siapa ya?" tanya Pak Endi ramah. "Saya teman kantor Bu Leni, isteri Bapak. Ini berkas kerjanya. Kemarin, tertinggal di mobil saya. Karena hujan deras, Bu Leni numpang ke mobil saya. Kebetulan rumah saya cuma beda satu gang dari sini. Mari. Assalamu’alaikum!" ucap si pemuda sambil senyum ramah dan berlalu.
Pak Endi tetap mematung, memandangi kepergian si pembawa berkas.([email protected])