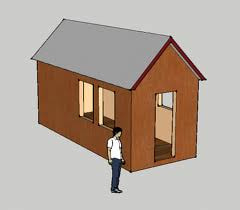Malu merupakan salah satu hiasan wanita. Dengan malulah wanita menjadi tambah cantik dan menarik. Adakalanya, tidak cuma wanita yang bisa berhias malu. Karena laki-laki pun bisa menjadi sangat pemalu.
Pertemuan sepasang suami isteri adalah juga pertemuan dua sayap yang sebelumnya terpisah. Tak mungkin ada burung yang bisa terbang dengan satu sayap. Sepasang sayap suami isteri itulah yang membawa terbang seribu satu sifat manusia kepada sebuah titik keseimbangan.
Idealita pun bertanya, mungkinkah dua sayap itu tersusun mulus: tepat, akurat, tanpa ketimpangan. Dan realita pun menjawab, kadang ada sayap yang terbentuk agak terbalik.
Sudah menjadi kewajaran kalau laki-laki punya sifat berani, cuek, dan tegas. Begitu pun dengan wanita. Biasa kalau wanita tampil lembut, anggun, dan pemalu. Dua titik kewajaran yang nyaris bertolak belakang itulah yang akhirnya seimbang dalam ikatan suami isteri.
Namun, tidak semua yang wajar selalu datar. Adakalanya naik, dan turun. Boleh saja orang menganggap kalau seorang suami itu tegas dan cuek. Dan isteri lembut nan anggun. Tapi, kenyataan bisa membuktikan kalau ada suami yang justru sangat pemalu. Hal itulah yang kini dirasakan Bu Imah.
Ibu dua anak ini mungkin tergolong wanita yang mudah adaptasi. Luwes. Mudah bergaul. Kalau dipikir-pikir, sifat ini merupakan cap baru buat Bu Imah. Karena sebelum menikah, ia agak pendiam. Jangankan supel, bisa bertahan satu jam saja di keramaian sudah jadi prestasi luar biasa. Kenapa bisa begitu drastis?
Mengenang itu, Bu Imah jadi senyum sendiri. “Lucu memang,” bisik batinnya pelan. Ternyata, selama lima tahun menikah banyak hal terjadi.
Bisa dibayangkan jika orang pendiam bertemu pemalu. Suasana begitu senyap. Persis seperti kampung tanpa listrik. Siang sepi, malam gulita. Yang terdengar cuma suara bersin, batuk, dan tangis anak-anak penghuni kampung. Seperti itulah suasana di bulan-bulan pertama pernikahan Bu Imah.
Lambat tapi pasti, suasana lingkungan mengubah Bu Imah. Tinggal di rumah mertua memang bukan tempat yang cocok buat yang pendiam. Apalagi yang selalu di rumah. Mau apa-apa serba susah. Mau nyelonong ke dapur takut dikritik, ingin makan di luar nggak cukup uang. Wah, repot!
Mau tidak mau, Bu Imah belajar ngomong. Tak mudah, memang. Bulan pertama masih kikuk, bulan kedua keluar keringat dingin. Namun, pepatah memang benar: pengalaman guru yang terbaik. Dua tahun terus uji coba, perubahan pun terasa. Seolah, ayah ibu mertua, kakak ipar dan kemenakan Bu Imah menjadi pelatih alami hingga Bu Imah pintar gaul.
Belum lagi dengan suasana tetangga yang sama sekali berbeda dengan rumah orang tua Bu Imah. Di sekitar rumah mertua, Bu Imah menemukan tetangga-tetangga yang hiper-aktif. Sebentar-sebentar berkunjung. Ngobrol, ngerumpi. Suasana jadi begitu ramai. Perubahan sifat Bu Imah jadi makin sempurna.
Menariknya, perubahan seperti itu tak dialami suami Bu Imah. Selama bertahun-tahun menikah, sifat suami Bu Imah begitu-begitu saja. Sedikit pun tak berubah. Tetap saja pemalu. Itulah di antara sebab kenapa Bu Imah masih tinggal di rumah mertua. Padahal, anak sudah dua.
Aneh, memang. Pendatang berubah, tuan rumah masih seperti dulu. Semula, Bu Imah mengira itu cuma terjadi dengannya. Karena baru kenal, wajar kalau seorang suami masih malu. Ternyata, sama tetangga yang entah sudah berapa tahun dikenal pun seperti itu. Malu. Perubahan cuma terjadi antara suami dengan Bu Imah. Sementara dengan tetangga, orangtua, sanak keluarga, dan teman-teman dekat Bu Imah tetap tidak berubah. Malu dan malu!
Wajar jika dunia suami Bu Imah begitu terbatas. Rumah, kantor, teman ngaji, dan kembali ke rumah. Tidak heran jika teman Bu Imah sering gagal menemukan alamat rumah Bu Imah. Bukan alamatnya yang salah. Tapi, nama suami Bu Imah yang jadi patokan nyaris tak dikenal tetangga. “Siapa? Kayaknya nama itu nggak tinggal di sini!” ucap para tetangga kerap membingungkan si pencari alamat.
Bahkan saat ini, masyarakat sekitar lebih kenal Bu Imah ketimbang suaminya yang penduduk lama di situ. Tidak jarang beberapa ibu-ibu sekitar rumah bertanya ke Bu Imah, “Suami ibu orang mana, sih?”
Tiap ada undangan, apa saja: walimahan, ulang tahun, syukuran, akikahan; prosentase kehadiran suami Bu Imah jauh tertinggal dibanding sang isteri. Rumus yang berlaku: kalau ada suami, pasti ada isterinya; tapi belum tentu sebaliknya.
Pernah Bu Imah menyusun strategi. Ia pura-pura tidak bisa hadir ke sebuah undangan tetangga karena tidak enak badan. Saat itu juga, suami Bu Imah bingung. Padahal, yang ngundang tergolong teman dekat ayah mertua Bu Imah. Spontan, mertua Bu Imah meminta anaknya untuk hadir. Tampak dari wajah suami sesuatu yang beda: pucat, keringat dingin, dan salah tingkah. Melihat itu, hati kecil Bu Imah cuma berujar, “Duh, mudah-mudahan niat baik ini tidak dicatat dosa sama Allah!”
Dengan susah payah, suami Bu Imah akhirnya siap berangkat. Baju batik yang dikenakannya tampak basah di bagian belakang karena keringat dadakan. Begitu pun sisiran rambut yang semula rapi, mulai semrawut tak menentu. “Yah, bismillah!” ucap suami Bu Imah sambil melangkah keluar rumah.
Melihat itu, Bu Imah menarif nafas lega. “Alhamdulillah! Berhasil juga,” ucap Bu Imah dalam hati. Sesaat setelah itu, ayah mertua Bu Imah bilang, “Sudah berangkat suamimu, Mah?” Setelah jawabannya positif, senyum pun menghias sang ayah. Tampaknya, ia berharap kalau anak bungsunya tidak mengecewakan.
Pagi itu begitu cerah ketika Bu Imah sedang bermain di halaman sama anak-anak. Baru saja, mereka melepas keberangkatan suami dan ayah tercinta ke tempat kerja. Tiba-tiba, seorang tetangga yang pernah mengundang syukuran menghampiri. “Bu Imah, kok kemarin tidak datang?” tanya sang tetangga ramah. “Anu, saya sedang tidak enak badan,” jawab Bu Imah sekenanya. “Oh gitu. Kenapa tidak diwakili. Apa suami Bu Imah juga nggak enak badan?” tanya sang tetangga lebih dalam.
Saat itu juga, wajah Bu Imah pucat. Ia seperti tersadar sesuatu. “Ah, suamiku!” ucapnya sambil memaksakan senyum ke arah sang tetangga. ([email protected])