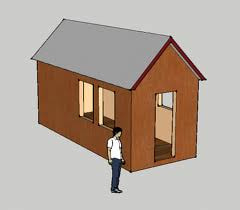Seorang anak punya penilaian sendiri tentang ayahnya. Penilaian itu muncul dari pengalamannya bersama ayah. Ada kesan ketika ayah menatap, saat ayah bicara, bila ayah marah, dan saat ayah jarang di rumah.
Begitulah perasaan seorang anak terhadap ayahnya. Ada banyak warna yang ia imajinasikan. Dan warna itu begitu kuat melekat dalam pikiran dan emosinya. Suatu saat, warna itulah yang kelak menuntunnya bagaimana menjadi seorang ayah.
Menurut penelitian Henker (1983), sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua dengan anak (termasuk emosi, reaksi dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan terjelma dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dahulu membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam ingatan dan terbawa ke dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam ingatan dan mengakibatkan stress. Ini artinya, terdapat “the unfinished business” dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya.
Memang, tak ada orang tua yang ingin mewariskan perilaku buruk buat anak-anaknya. Karena itu berarti buruk buat investasi generasi ke depan. Persis seperti anak-anak yang tidak menginginkan ketidakseimbangan ada pada orang tuanya. Dalam hal apa pun. Termasuk, perhatian dan kasih sayang.
Setidaknya, hal itulah yang kini diamati Andi. Bocah empat tahun ini kerap mendengar pertanyaan dari orang sekitarnya: tetangga, guru, ibu, nenek, bahkan pembantu. “Andi kalau besar mau seperti ayah, ya?” seperti itulah pertanyaan yang Andi dengar.
Mungkin, Andi memang perlu belajar banyak soal siapa ayahnya. Karena cuma ia yang belum bereaksi utuh seperti yang dirasakan orang-orang sekitarnya. Mereka begitu bangga punya orang terdekat yang dikagumi masyarakat. Ada yang menganggap ayah Andi sebagai guru, pejuang, bahkan teladan.
Orang-orang sekitar Andi mengenal ayahnya serba sempurna. Pengorbanannya buat masyarakat yang begitu besar. Hampir seluruh waktu ayah Andi tercurah buat orang banyak. “Ayahnya Andi memang orang hebat. Benar-benar aktivis sejati,” seperti itulah komentar yang didengar Andi.
Kemana pun Andi pergi, orang selalu mengaitkan Andi dengan ayahnya. “Andi pintar ya, seperti ayah!” Ada lagi yang sering bertanya soal ayah kalau ketemu Andi. “Andi, ayah sehat? Andi, ayah baik-baik saja?” Masih ada pertanyaan lain yang cuma dijawab Andi dengan senyum.
Tak seorang pun tahu apa arti senyum yang diperlihatkan Andi. Adakalanya, orang cuma menangkap pemandangan luar. Tapi, tidak mampu menyentuh isi yang ada di dalam. Terlebih, ungkapan dari seorang anak kecil.
Di balik senyum itu, Andi kerap termenung mencermati reaksi sekitar tentang ayahnya. Ia sendiri bingung. Apa yang salah dengan dirinya. Kenapa ia tidak sebangga ibu, kakak-kakak, atau orang-orang lain tentang ayah. Kenapa cuma dia yang menilai lain tentang ayah. Andai, ada yang berpikir sama dengan dia.
Sebenarnya, berkali-kali Andi berusaha untuk bangga. Tapi, tetap tidak bisa. Ia merasa ayah tidak sebagus yang dikira orang banyak. Andi menilai ayahnya tidak adil. Pelit. Tidak layak jadi teladan.
Andi kembali termenung. Ia cuma bisa mengamati gelak tawa teman-teman TK-nya. Ada yang asyik bermain ayunan, berkejar-kejaran, atau tenang duduk sambil menghisap permen. Mereka tampak gembira.
“Enaknya mereka,” ucap Andi dalam hati. Pasti mereka bahagia dengan ayah dan ibu. Pagi bertemu, malam bersama lagi. Bisa cerita ke ibu kalau nggak sreg sama ayah. Dan, bisa curhat sama ayah kalau nggak cocok sama ibu. Ah, mungkin di antara mereka ada yang minggu kemarin pergi berjalan-jalan sama ayah dan ibu. Puas rasanya menatap wajah ayah, senyumnya, dan mungkin marahnya.
Lebih setahun Andi berpikir tentang itu. Selama itu pula, pertemuannya dengan ayah tercinta bisa dihitung dengan jari. Andi bangun, ayah sudah pergi. Andi tidur, ayah masih di luar. Hampir tiap hari. Termasuk Minggu. Saat-saat yang bisa membuat puas hati Andi cuma satu: ketika ayah sakit.
Saat itulah, ia bisa puas menatap wajah ayah. Membelai tangan ayah. Memegang jemarinya yang tampak kurus. Sayangnya, ayah tak bicara banyak. Kecuali, batuk kecil atau mendengkur. “Ayah butuh istirahat, Andi!” tegur ibu suatu kali.
Itulah kesempatan yang sangat berharga buat Andi. Bahkan, ia berharap kalau ayahnya sering sakit.
Kebingungan Andi kerap menggiringnya pada sebuah pertanyaan sederhana: apa yang dicari ayah. Lebih pentingkah sesuatu yang ayah cari itu sehingga tak lagi perlu menemuinya, menyapanya, atau menegurnya. Ingin rasanya ia bercerita soal mobil mainannya yang rusak ke ayah. Ingin sekali ia duduk di pundak ayah, seperti anak-anak lain yang pernah ia lihat. Seperti Dede, Budi, Jejen, Dodi.
Mungkin, orang-orang akan takjub kalau tak sekali pun ayah Andi memarahi atau bertindak kasar terhadap anaknya. Tapi bagi Andi, itu sudah kemestian. Gimana mau memarahi, ketemu saja hampir tak pernah. Protes Andi suatu kali.
Andi tampak serius menatap buku raport yang baru diambil ibunya. Dibukanya raport itu perlahan. Mulutnya tampak mengeja sesuatu. Sejenak, ia pun akhirnya mengangguk pelan. “Ah, ini ya nama ayahku!”
([email protected])