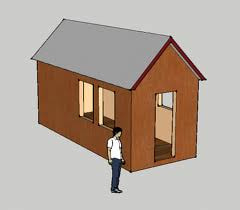Lebaran dan pulang kampung buat sebagian keluarga persis seperti ketupat dengan sayurnya. Terasa ada yang kurang jika satu terlewatkan. Cuma masalahnya, tidak semua keluarga mampu mengolah ‘sayur’ pulang kampung. Kalau pun ‘sayur’ ada, tetap saja terasa hambar.
Pulang kampung saat Lebaran punya dua sisi yang berbeda. Bahkan, mungkin bisa berlawanan. Satu sisi begitu menyenangkan: bisa ketemu bapak-ibu, kakek-nenek, pakde-pakle, dan lain-lain; bisa juga kangen-kangenan dengan tempat kelahiran. Berputarlah kenangan lama semasa kecil dan remaja. Pokoknya, sangat menyenangkan.
Sisi lain adalah yang kurang mengenakkan. Terutama buat mereka yang punya halangan. Ada halangan fisik seperti mabuk di kendaraan, juga halangan lain yang bukan cuma tidak mengenakkan tapi juga membingungkan. Apalagi kalau bukan urusan kantong.
Buat mereka yang di Jakarta dan kampungnya masih menyatu di peta kepala pulau Jawa, mungkin tidak begitu berat. Kisaran dana yang keluar masih hitungan ratusan ribu. Tapi buat mereka yang peta kampungnya ada di badan dan kaki Pulau Jawa, hitungannya mungkin bisa nyentuh jutaan. Dan yang parah buat mereka yang kampungnya tidak ada di peta Pulau Jawa, kantong yang terkuras bisa di atas dua juta rupiah. Bahkan mungkin, puluhan juta. Laa haula walaa quwwata illa billah.
Enak atau susah, pulang kampung tetap jadi pilihan. Ini karena pulang kampung punya makna lain dari sekadar kangen-kangenan. Yaitu, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Setidaknya, itulah yang kini diperjuangkan Bu Wiwin.
Ibu dua anak ini memang bukan asli Jakarta. Ia menikah karena pertemuan jodoh di kampus yang berdomisili di Jakarta. Ketika menjelang akhir masa kuliah, Allah menjodohkannya dengan pemuda di Jakarta. Menariknya, sang pemuda yang menjadi suami Bu Wiwin pun ternyata juga bukan orang Jakarta. Ia cuma sedang bekerja di Jakarta. Terjadilah perpaduan antara Bu Wiwin yang asli Jogya, dan suaminya yang keturunan Bengkulu.
Tak ada masalah, memang. Biar jauh dari orang tua, Bu Wiwin dan suaminya akur-akur saja. Problem baru muncul ketika Lebaran datang. Pasalnya, baik Bu Wiwin atau suami, keduanya butuh pulang kampung. Bu Wiwin ditunggu bapak dan ibu di Jogya, sementara suaminya ditunggu orang tuanya di Bengkulu. Repot kan?
Nggak mungkin pisahan sementara. Bu Wiwin ke Jogya tanpa suami, dan suaminya ke Bengkulu tanpa isteri. Lalu, gimana dengan anak-anak? Dan lebih nggak mungkin lagi, mereka berkeliling dua kampung dalam satu Lebaran.
Akhirnya, saat Lebaran tahun lalu sudah ada kesepakatan. Isinya, masing-masing pulang kampung dua Lebaran sekali. Satu lebaran ke kampung suami. Berikutnya ke kampung isteri. Dan tahun lalu, sudah ke Bengkulu. Lebaran tahun ini, harusnya ke Jogya.
Inilah saat-saat yang paling ditunggu Bu Wiwin. Kangennya bisa ketemu bapak ibu. Bu Wiwin yakin, begitu pun dengan kedua orang tuanya. Pasalnya, Bu Wiwin anak bungsu. Satu-satunya anak perempuan lagi. Tiga kakaknya laki-laki. Dan semuanya tinggal di kampung. “Duh, Bapak pasti sudah nunggu-nunggu,” suara batin Bu Wiwin mulai merajuk. Di Lebaran kali ini, cuma ada satu tekad Bu Wiwin: apa pun yang terjadi, harus pulang kampung!
Kekangenan Bu Wiwin kian menjadi ketika bapak dan ibu tidak nelpon-nelpon hingga satu bulan. Selama Ramadhan, praktis Bu Wiwin hidup tanpa sentuhan ‘kasih sayang’. Tanpa bisa manja-manja. Suatu hal yang biasa ia lakukan ketika masih lajang. Padahal biasanya, hampir seminggu sekali bapak atau ibu telpon ke rumah Bu Wiwin. Kalau mau telpon balik sangat tidak mungkin. Soalnya, bapak ibunya tinggal di pedesaan yang belum tersangkut kabel telpon.
Apa bapak ibu sedang sakit? Bu Wiwin kian gelisah. Di telponnya yang terakhir, bapak cuma bilang kangen saja. Bapak juga bilang, ingin lihat rumah anak kesayangannya di Jakarta. Tapi itu tergolong sulit buat mereka berdua. Di samping usianya yang enam puluhan, mereka baru sekali datang ke Jakarta. Itu pun karena ada undangan wisuda di kampus Bu Wiwin. Dan lagi, kalau anaknya masih bisa ke kampung, kenapa mesti orang tua yang ke kota. Kualat, dong!
Duh, gimana kabar bapak dan ibu. Apa mereka sehat-sehat saja di Jogya. Apa rematik bapak kumat lagi. Kenapa saya tidak dikabari. Pikiran Bu Wiwin terus berputar. Campur aduk antara gelisah, kangen, dan bingung.
Bingungnya, justru di giliran pulang ke kampungnya, tabungan Bu Wiwin dan suami lagi ludes. Itu terjadi karena anak pertama Bu Wiwin sempat terserang tipes dan dirawat di rumah sakit selama seminggu. “Duh, cobaan!”
Sesaat kemudian, Bu Wiwin tersadar. “Astaghfirullah!” gumamnya pelan. Cobaan memang bukan untuk dikeluhkan. Tapi harus diperjuangkan, agar alur hidup terus bergulir normal. Yap, harus dicari jalan keluar supaya bisa dapat duit buat pulang kampung. Tapi, kemana?
Mulailah Bu Wiwin dan suami nyari-nyari pinjaman. Mulai ke kantor suami, teman dekat, bahkan tetangga. Ternyata, tidak gampang pinjam uang di saat Lebaran. Supaya bisa dapat uang satu juta saja, mesti mengumpulkan pinjaman di tiga sumber. Itu pun memakan waktu satu minggu.
Walau Lebaran sudah lewat satu minggu, Bu Wiwin dan keluarga tetap pulang kampung. Mungkin di sinilah hikmahnya, kereta ke Jogya jadi tidak begitu penuh. Semua bisa duduk dengan nyaman.
Rasa kangen Bu Wiwin hampir tidak bisa lagi tertahan ketika rumah yang dituju terlihat jelas. “Pak, Bu! Wiwin pulang!” teriak Bu Wiwin sekeras-kerasnya. Teriakan kian ramai saat anak-anak Bu Wiwin ikut-ikutan. Tapi, tak satu suara pun menyahut. Rumah itu begitu sepi. Kemana bapak dan ibu?
“Eh, Wiwin, tho! Anaknya sudah sembuh?” suara seorang tetangga yang muncul menghampiri. “Lha, memangnya Nak Wiwin ndak tahu. Bapak dan ibu kan ke Jakarta. Ke rumah Nak Wiwin. Baru tadi pagi berangkat!” jelas sang tetangga agak prihatin.
“Bapaaak…! Ibuuu…!” teriak Bu Wiwin agak histeris. Ia pun menangis sejadinya. ([email protected])