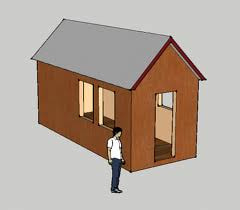Keluarga tak ubahnya seperti bus. Suami sebagai sopir dan isteri sebagai kondektur. Sopirlah yang menentukan arah, kecepatan, dan nyaman tidaknya bus melaju. Sementara kondektur mengawasi keadaan penumpang. Bahkan tidak jarang, kondektur pula yang meluruskan kaca spion, berurusan dengan polisi atau bahkan mengurus ban bocor.
Keseimbangan merupakan idaman tiap keluarga. Seimbang materi, juga spiritual. Keseimbangan juga yang menjadikan tiap anggota keluarga berada pada posisinya masing-masing. Siap dan siaga dengan tugas-tugas rutin mereka.
Seorang suami yang menyadari pentingnya keseimbangan akan berupaya sungguh-sungguh menunaikan tugasnya. Begitu pun dengan isteri dan anak-anak. Semuanya sibuk, tapi tetap pada rel yang sudah ditentukan. Saat itulah terjadi kerja sama: kerja bersama yang sama-sama kerja.
Repotnya, ketika satu pos tidak tertangani dengan baik. Maka, akan terjadi ketidakseimbangan di pos yang lain. Itulah yang saat ini dialami keluarga Bu Nini. Ibu lima anak ini benar-benar kerepotan dengan urusan yang kelihatan sederhana. Tapi, terasa begitu sulit.
Beberapa hari terakhir ini, Bu Nini agak bingung dengan bocoran air di atas rumahnya, persis di ruang dapur. Kian hari tetesannya kian banyak. Awalnya cuma setengah ember buat sekali hujan. Sekarang, tiga kali ganti ember masih belum cukup. Bahkan, sumber tetesan tidak lagi satu. Tapi, mulai menyebar ke kamar tidur. Benar-benar merepotkan!
Sambil menatap ke arah langit-langit rumah yang kian basah, Bu Nini mulai berpikir. “Sebenarnya, tugas siapa ya ngurus atap bocor. Saya apa suami? Kayaknya jelas: suami!” Kesimpulan itu begitu kuat ketika sulit buat Bu Nini membayangkan kayak apa repotnya naik-naik ke atap rumah.
Tapi, satu pekan ini, suami tidak sedang di rumah. Ada tugas kantor yang mengharuskan suami Bu Nini pergi keluar kota. Paling cepat satu pekan baru bisa pulang. Biasanya, lebih. Bahkan, bisa dua kali lipat dari waktu yang direncanakan.
Bu Nini bingung sendiri. Kalau sampai dua pekan nggak diperbaiki. Wah, bisa-bisa kamar tidurnya bocor semua. Sementara, hujan belum ada tanda-tanda akan mereda. Ia hampir-hampir tidak lagi merasakan nikmatnya anugerah Allah yang amat mahal itu.
Buat Bu Nini, hujan jadi lebih dekat ke musibah ketimbang anugerah. Bayangkan, lagi enak-enak tidur karena capek ngurus rumah seharian, tiba-tiba mimpi kehujanan. Dan yang mimpi seperti itu bukan cuma milik Bu Nini. Empat dari lima anaknya pun punya mimpi yang sama. Kecuali si bayi yang tidur di tempat khusus. Rupanya, mimpi yang seragam itu memang bukan sekadar mimpi. Tapi memang sebuah kenyataan. Bu Nini dan empat anaknya sama-sama merasakan tetesan air hujan.
Pernah Bu Nini panik ketika tersadar dari tidur. “Siapa yang ngompol nih? Siapa?” suara Bu Nini sambil memegang seprei tempat tidurnya yang terasa basah. Walau matanya masih terpejam, feelingnya begitu kuat mengucapkan itu. Padahal, tak satu anak pun yang tidur bersama Bu Nini. Basah itu cuma tetesan air dari atap.
Ah, siapa yang bisa memperbaiki? Lagi-lagi Bu Nini termenung. Tidak mungkin ia menyuruh anak-anaknya. Masih kecil-kecil. Si sulung saja baru kelas lima SD. Mau minta tolong sama tetangga, tak enak hati. Dan lagi, di siang hari cuma ada ibu-ibu. Suami-suami mereka sudah keluar rumah.
“Duh, siapa ya?” keluh Bu Nini memeras pikiran. Masak cuma urusan mengganti genting bocor saja, ia mesti menyewa tukang bangunan. Mana ada yang mau? Lagian, di daerah komplek seperti ini teramat sulit mencari buruh bangunan.
Mau nyuruh Mbok Iyem nggak mungkin. Selain sudah tua, pembantunya itu latahan. Gimana kalau sedang di atas genting tiba-tiba kumat. Wah, bisa repot dua lipat.
Hujan terus mengguyur seperti tak kenal kompromi. Dan, bocor kian membuat tetesan air menyebar. Sudah dua anak Bu Nini yang terpeleset jatuh karena lantai licin kena air. Satu kasur pun kian kuyup. Ah, Bu Nini sudah tidak lagi mampu menahan sabarnya.
Ketika malam mulai larut, Bu Nini diam-diam keluar rumah. Anak-anak tampak sudah tertidur pulas. Begitu pun dengan Mbok Iyem. Hujan turun rintik-rintik. Perlahan, Bu Nini mengangkat tangga yang sudah ia siapkan sejak sore tadi. Tangga itu ia tegakkan pada atap rumahnya. Sejenak, Bu Nini keluar halaman. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. “Ah, aman. Tak ada orang…,” ujarnya dalam hati.
Pelan dan berhati-hati sekali, Bu Nini menaiki tangga. Sambil tangan kirinya memegang senter, tangan kanannya mencekal gagang tangga erat-erat. “Ah, jadi ingat waktu anak-anak dulu. Ketika ngambil layang-layang di atas genting,” kembali batin Bu Nini berujar geli.
Beberapa saat, ia berhenti di atas atap. Tangannya mulai memainkan senter yang sejak tadi ia pegang. Bu Nini seperti mencari sesuatu. “Oh, itu sumbernya!” ucap Bu Nini mulai terdengar. Beberapa saat, ia menuruni tangga. Juga dengan pelan dan hati-hati.
Ia pun mengambil tiga genting cadangan yang sudah ia siapkan di pojok halaman. Sambil tangan kiri memegang tiga genting, tangan kanan Bu Nini memegang erat gagang tangga. Berhati-hati sekali ia menapaki anak tangga tanpa alas kaki. “Bismillah,” ujar Bu Nini spontan.
Setibanya di atas, ia seperti mengingat sesuatu. “Ya Allah, senternya masih di bawah!” Dengan tergesa-gesa, ia pun menuruni tangga. Tanpa sadar, pijakannya tak lagi pas di anak tangga. Ia terpleset. Dan, “Brakkk!” Bu Nini terpelanting dari tangga. Karena tangan kanannya masih memegang gagang tangga, tangga itu ikut terbalik. Dan bunyi itu adalah benturan antara tangga dengan pagar halaman rumah Bu Nini. Suara itu spontan membangunkan para tetangga. Dan tentu saja, Mbok Iyem dan anak-anak.
Menekuni hidup berumah tangga memang mirip dengan mengendarai bus. Repotnya akan sangat terasa ketika sopir berhalangan. Dengan sangat terpaksa, kondektur pun mesti merangkap sopir. Itupun kalau bisa menyetir.