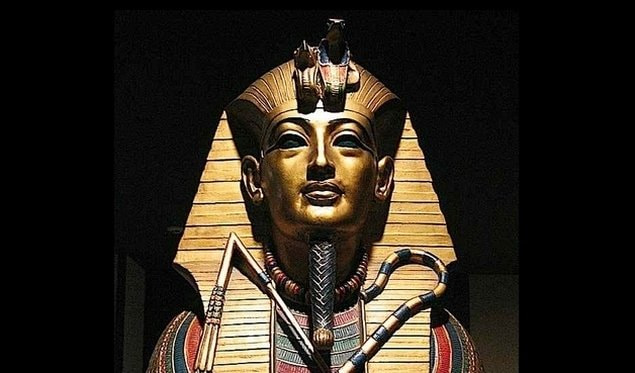Dua orang tokoh partai bertemu di tv. Satunya mewakili partai nasionalis. Satunya mewakili partai Islam. Keduanya bersepakat bahwa tidak ada dikotomi (perbedaan) antara nasionalisme dan Islam. Di acara tv itu wakil partai nasionalis memekikkan : merdeka! Dibalas wakil dari partai Islam memekikkan : merdeka! Tiga kali. Sebagai wujud rasa nasionalisme yang tinggi. Lalu, keduanya menyatakan dan bersepakat tidak ada dikotomi antara nasionalisme dan Islam. Dengan pengertian masing-masing. Gayung bersambut. Tak bertepuk sebelah tangan. Golonggan nasionalis dan Islam berpadu dalam tataran filosofis, dan akan melaksanakan dalam implementasi. Bentuknya sedang digagas. Mungkin koalisi atau bahasa lainnya musyarokah.
Masih di bulan ramadhan wacana tentang nasionalisme dan Islam berlangsung. Melibatkan wakil dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Mengapa nasionalisme dan Islam harus tiba-tiba menjadi topik pembicaran yang serius dikalangan para pemimpin? Tak lain, karena adanya kebutuhan, dan keinginan menjalin sebuah kerjasama politik. Apakah mungkin golongan nasionalis bisa bekerjsama dengan golongan Islam? Atau sebaliknya. Apakah mungkin golongan Islam bisa bekerjasama dengan golongan nasionalis? Dengan tujuan membangun sebuah kekuasaan? Barangkali persoalannya bukan hanya berhenti sampai di situ.
Tapi, apakah mungkin golongan Islam, bersedia memberikan dukungan politik (ideologis) kepada golongan nasionalis? Meskipun, sudah ada preseden, seorang tokoh Islam telah menjadi wakil presiden dari seorang presiden wanita, yang mewakili golongan nasionalis. Di pemilu 2004, yang lalu, seorang pimpinan ulama, dicalonkan mendampingi calon presiden wanita, dari golongan nasionalis. Apakah preseden ini dapat dijadikan dasar perspektif politik Indonesia di masa depan? Kerjasama antara golongan nasionalis dan Islam? Khususnya, dalam membangun kekuasaan politik, yang mempunyai tujuan-tujuan luas, menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, sejahtera, bagi seluruh rakyat?
Kita, sudah mempunyai pengalaman, yang panjang, bagaimana ketika, kekuasaan dikelola oleh golongan nasionalis. Di mana mereka menunjukkan tidak adanya toleransi terhadap golongan Islam. Tidak hanya itu. Mereka, juga tak jelas visi nasionalisme, yang menjadi bagian penting ideologi dari gerakan mereka. Implementasi dari wujud nasionalisme sebagai sebuah ideologi, masih tetap ‘ambigu’ (mendua) dalam segala aspek kehidupan. Mereka menentang segala bentuk pengaruh Barat. Kenyataannya, mereka tak dapat mengatasi tarikan pendulun, dari ideologi lain, yang lebih ekstrim, yaitu komunisme. Nasionalisme hanya menjadi sebuah jargon politik, dan phobia terhadap Barat, tapi menjadi satelit dari ideologi materialisme lainnya, yaitu komunisme. Seperti yang terjadi diawal masa kemerdekaan, dan tergambar dalam diri Soekarno. Soekarno tidak hanya anti Islam, tapi menjerumuskan Indonesia ke dalam arus besar gerakan materialisme internasional yang atheis (anti tuhan), dan berakhir dengan sebuah tragedi kemanusiaan, yaitu perang saudara, di tahun 1965.
Tak dapat dilupakan. Semua tercatat dalam sejarah. Ketika Indonesia masih sangat dini, berupa ‘bayi’ yang baru lahir, baru merdeka dari penjajah, ketika masih mencari bentuk dan format, serta landasan kehidupan bersama, bagi membangun sebuah bangsa dan negara (nation state). Polarisasi sudah terjadi. Polarisasi bukan hanya menyangkut kebijakan, tapi menyangkut hal yang bersifat filosofis dan ideologis. Golongan Islam ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, sedangkan golongan nasionalis ingin menjadikan Pancasila, yang ‘man made’ (buatan manusia) itu menjadi dasar negara. Dan, berakhir dengan tragedi. Sama. Seperti ketika berakhirnya kekuasaan Soekarno juga tragedi. Waktu itu, di tahun 1959, Soekarno membubarkan konstituante, yang menjadi sarana bermusyawarah diantara golongan-golongan yang ada. Soekarno mengeluarkan : ‘Dekrit’. Kembali ke UUD ‘45. Dekrit adalah sebuah kata, yang nantinya menjadi awal, Indonesia menuju bentuk kediktoran, dan perpecahan, serta kehancuran. Soekarno dan golongan nasionalis, tak menginginkan Islam menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan, bukan hanya itu, Soekarno memenjarakan para pemimpin Islam,yang berbeda pendapat dengannya.
Masih ingat? Di era reformasi ini? Sebuah partai yang memposisikan dirinya dari golongan nasionalis. Ketika berkuasa tak juga menunjukkan diri sebagai partai yang benar-benar nasionalis. Kebijakannya dibidang ekonomi, tak populis, yang berpihak kepada rakyat kecil. Kebijakan ekonominya tetap pro-pasar (kapitalis). Orang-orang yang menangani tim ekonomi adalah orang-orang yang dekat lembaga multilateral seperti IMF. Tak ada tawaran baru yang lebih baik, khususnya dalam mengatasi krisis ekonomi, dengan konsep yang lebih mandiri, tanpa bergantung Barat. Di sini hanyalah menggambarkan ‘ambivalensi’ tentang nasionalisme, ketika berhadapan dengan globalisasi, yang akhirnya tak mampu mengubah kondisi krisis.
Belum lagi kebijakan terhadap Islam. Isu-isu yang dianggap berbau Islam, pasti mendapat penolakan. Tak mau memberikan apresiasi positip. Seperti belakangan ini, masalah undang-undang pendidikan, mendapat tantangan yang kuat, khususnya yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Karena, dalam rancangan undang-udang itu, tujuan pendidikan adalah menciptakan anak didik menjadi beriman dan bertaqwa. Mereka juga memberikan penolakan terhadap undang-undang yang ingin membatasi pamer syahwat. Sampai sekarang undang-undang ini masih terkatung-katung. Belum lagi, soal perda-perda, yang belakangan ini muncul, di daerah-daerah, yang ingin melarang berbagai bentuk kemaksiatan, juga dituding sebagai langkah-langkah melaksanakan syariah Islam.
Nampaknya, memang tidak bisa bertemu antara nasionalisme dan Islam dalam tataran filosofis ideologis, dan implementasi. Bukan hanya filosofis dan ideologis yang berbeda, tapi dalam bentuk implementasinya juga berbeda. Karena landasannya berbeda, yang tak mungkin dapat disatukan dan diwujudkan. Kalau pun pernah terjadi, tak lain, lebih pada kekuasaan semata. Tapi, secara ideologis, tak pernah dapat disatukan, dan ibaratnya seperti minyak dengan air. Dulu, ketika zaman Soekarno pernah golongan Islam mau bersedia mendukung Soekarno, ketika membentuk kabinet ‘kaki empat’ Nasakom, di mana golongan nasionalis, agama (Islam), dan komunis, disatukan dalam kekuasaan, tapi itu tak lebih dari akal-akalan, dan tak berumur panjang. Jadi, kalau sekarang masih ada obsesi, yang menginginkan penyatuan antara golongan nasionalis dan Islam, itu hanyalah khayalan, atau manipulasi politik, yang sifatnya artifisial.
Di awalnya, faham nasionalisme, sebuah gerakan yang tertuju bagi kemerdekaan. Gerakan ini ini terilhami revolusi Prancis, yang melawan para raja dan kaum borjuis, yang menindas rakyat. Tapi, gerakan ini, tak lebih dari manipulasi orang-orang Yahudi di Eropa, yang sudah lama diperbudak para raja, gereja, dan kaum bangsawan. Karena itu, relevansi bagi dunia ketiga, khususnya negara-negara Islam, tak ada. Karena, justru negara-negara Islam di jajah dan perbudak penguasa Eropa, yang sangat ambisius dan ekspansif.
Jika ada yang merasa paling berhak menerima gelar sebagai ‘nasionalis’ adalah golongan Islam. Karena, mereka yang lebih mencintai tanah air. Mereka lebih sungguh-sungguh dalam membela tanah airnya. Mereka yang lebih banyak mengorbankan diri, membebaskan negaranya dari penjajahan dan perbudakan. Mereka yang melawan hegemoni kaum penjajah dan tiran Barat. Ketika,negara-negara Islam di jajah dan diperbudak, tokoh seperti Mohammad Bin Badis, tokoh pejuang di Aljazair, yang berjuang membebaskan negaranya dari penjajahan. Omar Muchtar, pejuang kemerdekaan Libya, yang berjuang dengan penuh semangat, yang akhirnya digantung penjajah Itali. Di Mesir, Hasan al-Banna, berjuang memerdekan negaranya dari penjajahan Inggris, dan berakhir dengan kematiannya, ditembak para kolaborator penjajah. Shalahuddin al-Ayubi, membebaskan al-Aqsha, dari para Salibis. Shalahuddin, hanya dengan 9.000 tentaranya, melawan gabungan tiga negara, Inggris, Jerman dan Prancis, yang mereka mengerahkan 300.000 pasukan Salib, yang sangat terkenal. Kemenangan Shalahuddin, yang akhirnya menciptakan Yarusalem, menjadi kota yang damai bagi seluruh agama.
Di era ini, kaum muslimin berjuang membebaskan tanah air nya, seperti di Iraq, Afghanistan, dan Palestina, dari penjajahan dan perbudakan, yang dilakukan Barat, dan Israel. Mereka bukan hanya sebagai seorang ‘nasionalis’, tapi ajaran agama (ideologi) mereka, tak pernah membolehkan negaranya dikuasai dan dijajah oleh asing. Maka, golongan Islam adalah mereka yang paling mencintai tanah airnya, dan memiliki kesadaran yang utuh terhadap tanah airnya. Membebaskan negaranya dari penjajahan adalah kesadaran yang sifatnya inherent (melekat), dan tak dapat ditawar-tawar.
Wacana tentang nasionalisme dan Islam, yang akhir-akhir digagas para pemimpin, tak ada yang serius dan substantive, dan mempunyai tujuan bagi masa depan Indonesia. Semuanya, tak lebih dari usaha dagang sapi, yang ingin bagi-bagi kekuasaan dengan legitimasi ideologi dan agama. Wallahu’alam. (mhi).