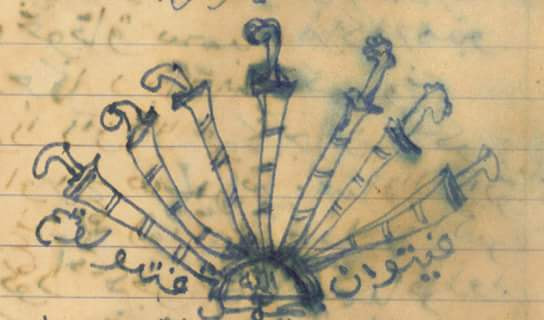Turki merupakan suatu negeri yang memiliki kisah panjang tentang jatuh bangunnya peradaban. Di negeri ini pula Islam pernah sedemikian bercahaya gemerlap tatkala Kekhalifahan Islam Turki Utsmani masih berdiri kokoh. Dan seorang Abdullah ‘Azzam, pernah pula berlinang airmata kesedihan ketika menulis satu demi satu kalimat yang diuntainya menjadi sebuah buku berjudul ‘Pelita Yang Hilang’. Turki merupakan pelita Islam di gerbang Eropa. Sebab itu, musuh-musuh Allah senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk memadamkan pelita tersebut.
Turki merupakan suatu negeri yang memiliki kisah panjang tentang jatuh bangunnya peradaban. Di negeri ini pula Islam pernah sedemikian bercahaya gemerlap tatkala Kekhalifahan Islam Turki Utsmani masih berdiri kokoh. Dan seorang Abdullah ‘Azzam, pernah pula berlinang airmata kesedihan ketika menulis satu demi satu kalimat yang diuntainya menjadi sebuah buku berjudul ‘Pelita Yang Hilang’. Turki merupakan pelita Islam di gerbang Eropa. Sebab itu, musuh-musuh Allah senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk memadamkan pelita tersebut.
Konspirasi Yahudi Internasional-lah, lewat seorang Yahudi dari Dumamah bernama Mustafa Kemal, yang meruntuhkan kekhalifahan Turki Ustmaniyah. Sejak itu, Mustafa Kemal menghancurkan semua simbol-simbol keIslaman dari negeri tersebut dan membunuh siapa saja yang berani menghalang-halanginya.
Setelah kekhalifahan hancur, Mustafa Kemal segera memberlakukan hokum sekularisme di negeri tersebut. Semua yang terkait dengan simbol-simbol keIslaman, walau sekecil apa pun, menjadi sesuatu yang dilarang. Barangsiapa yang masih mempergunakannya maka akan diseret ke penjara. Adzan pun yang di mana-mana mempergunakan bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Allahu Akbar menjadi Allahu Buyuk. Jangan tanya soal hijab atau jilbab, semuanya dicampakkan jauh-jauh.
Sekularisme yang dilancarkan Mustafa Kemal didukung penuh oleh angkatan bersenjata Turki yang memang telah dikondisikan jauh-jauh hari oleh jaringan Yahudi Internasional. Sampai hari ini pun, militer Turki dikenal sebagai penjaga nilai-nilai sekularisme paling depan dan senantiasa siap untuk memberangus siapa pun yang ingin meruntuhkan nilai-nilai sekularisme Turki tersebut.
Sistem Sekuler Bernama Demokrasi
Sebelum berkuasanya Mustafa Kemal, Turki yang masih menganut sistem kekhalifahan menganut sistem Syuro, bukan demokrasi. Ada perbedaan sangat prinsipil di antara keduanya. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki satu suara, tidak perduli apakah dia itu seorang ulama yang bersih atau dia seorang koruptor, seorang pembunuh, seorang maling, seorang munafik, atau seorang penzina sekali pun. SIngkatnya, dalam demokrasi, suara ulama dan suara seorang penzina itu dianggap sama: satu suara.
Beda sekali dengan Syuro yang memang berasal dari Islam. Dalam sistem Syuro, orang-orang yang dikenal baik reputasinya, bersih, shalih, jauh dari hal-hal yang syubhat apalagi haram, memiliki keilmuan yang bagus, pemahaman yang lurus, dan semata-mata bekerja dan hidup demi menegakkan Islam, bukan ‘menunggangi’ Islam, maka orang-orang ini diangkat oleh khalifah dan duduk di dalam satu majelis yang disebut Majelis Syuro. Majelis yang berisi orang-orang yang bersih dan lurus, para ulama dalam arti sesungguhnya, dan menjadi wakil umat di dalam memutuskan segala apa yang diperlukan umat dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Walau demikian, rakyat kebanyakan bisa mengontrol Dewan Syuro ini dan memberi masukan-masukan yang sesuai dengan Islam. Jika ada pejabat negara yang sudah melakukan sesuatu hal yang keluar dari nilai-nilai Islam, maka umat berhak meminta Dewan Syuro agar mencopot orang tersebut dari jabatannya. Dan Dewan Syuro pun akan membahas hal tersebut bersama-sama dan memutuskan menurut kaidah Islam yang benar, bukan menurut kalkulasi politik praktis yang semata berdasar logika seorang manusia semata, apalagi berdasar kepentingan sesaat syahwat kekuasaan.
Di zaman Rasulullah, jabatan publik seperti hakim, gubernur, menteri, atau sebagainya merupakan amanah yang sangat berat pertanggungjawabannya di akherat kelak, sehingga banyak sahabat yang menolak ketika jabatan itu akan diserahkan kepadanya. Para sahabat dan para tabiin memahami dengan baik jika hakikat kemenangan dalam Islam diukur dari seberapa banyaknya umat yang telah menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam. Makin banyak umat yang tebina, maka kondisi masyarakat, bangsa, dan negara dengan sendirinya juga akan semakin baik.
Hal ini beda dengan partai-partai sekuler yang mengukur hakikat kemenangannya semata dengan jumlah sudah berapa banyak posisi gubernur, menteri, dan jabatan publik lainnya berada di tangannya. Partai Islam tidak demikian karena lebih mengutamakan pembinaan terhadap manusianya, bukan posisi atau jabatannya yang sejatinya merupakan amanah yang sangat berat pertanggungjawabannya.
Para sahabat yang hidup berdampingan dengan Rasulullah saja banyak yang menolak jabatan, bahkan banyak yang menangis ketika dipaksa menerima jabatan tersebut. Beda sekali dengan zaman kini di mana banyak orang yang malah memburu jabatan, bahkan dengan menghalalkan segala cara.
Di masa kekuasaan Mustafa Kemal, banyak aktivis Islam dijebloskan ke dalam penjara bahkan sampai harus menemui kematian. Sebab itu, dakwah dilakukan dengan sangat rahasia dan tertutup. Dalam kondisi masyarakat demikian maka tumbuh suburlah tarekat-tarekat sufiisme yang merupakan sebuah eskapisme dari kondisi masyarakat yang kering ruhiyah. Sejarah mencatat jika sufiisme selalu berkembang dengan pesat di saat tatanan masyarakat dan kekuasaan bersikap represif terhadap dakwah Islam.
Pelajaran berharga diambil oleh para aktivis Islam Turki saat angkatan bersenjata negeri tersebut mengkudeta Perdana Menteri Adnan Menderes dari Partai Demokrat yang berkuasa di tahun 1960-an. Saat berkuasa, Menderes melakukan sejumlah upaya yang dinilai militer Turki bisa menghancurkan asas sekularisme Turki seperti membolehkan adan kembali dilakukan dalam bahasa Arab, merenovasi masjid yang rusak, membuka kembali fakultas ushuludin, dan menghidupkan kembali lembaga penghapal Al-Qur’an.
Oleh militer Turki, Menderes bersama Ketua Parlemen Bultuqan, serta Menteri Luar Negeri Fathin Zaurli dijatuhi hukuman mati.(rizki, bersambung)