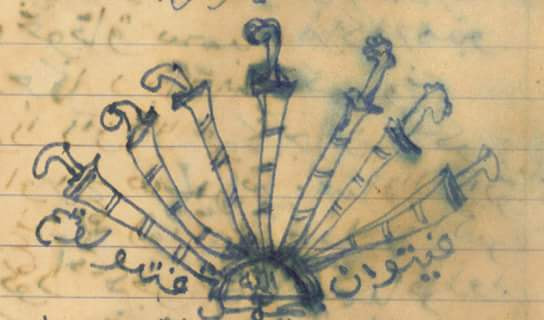Kemarahan tengah menyapu Amerika. Benar, kemarahan ini mungkin fenomena minoritas, bukan sesuatu yang mencirikan sebagian besar warga Paman Sam. Namun kemarahan minoritas juga kemarahan yang nyata; mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa haknya sedang diambil. Dan mereka keluar untuk membalas dendam.
Kemarahan tengah menyapu Amerika. Benar, kemarahan ini mungkin fenomena minoritas, bukan sesuatu yang mencirikan sebagian besar warga Paman Sam. Namun kemarahan minoritas juga kemarahan yang nyata; mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa haknya sedang diambil. Dan mereka keluar untuk membalas dendam.
Ini tentang orang kaya di Amerika.
Ini mungkin waktu yang mengerikan bagi banyak orang di negeri Amerika. Kemiskinan, terutama kemiskinan yang akut, melonjak dengan kemerosotan ekonomi; jutaan orang kehilangan rumah mereka. Orang-orang muda tidak punya pekerjaan; sebagian takut bahwa mereka tidak akan pernah bekerja lagi.
Namun jika Anda ingin mencari amarah politik yang nyata—misalnya seperti jenis kemarahan yang membuat orang membandingkan Presiden Obama dengan Hitler, atau menuduhnya pengkhianat— Anda tidak akan menemukannya di antara orang-orang Amerika yang menderita. Anda tidak akan menemukannya di antara orang yang tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan rumah mereka, atau kehilangan asuransi kesehatan mereka; tetapi yang mereka yang marah, benar-benar marah, adalah mereka yang tengah memikirkan bagaimana membayar pajak mereka yang tinggi.
Kemarahan orang-orang kaya menanjak cepat sejak Obama naik tahta. Pada awalnya, bagaimanapun, sebagian besar berfokus pada Wall Street. Jadi ketika majalah New York menerbitkan sebuah artikel berjudul "The Wail Of 1%," (Ratapan Satu Persen) yang berbicara tentang perusahaan yang menggerakan keuangan di negeri itu, ternyata ditebus dengan dana para pembayar pajak. Ketika milyuner Stephen Schwarzman membandingkan Obama dengan invasi Nazi di Polandia, proposal tersebut akan menutup celah pajak yang secara khusus akan memberikan manfaat kepada manager seperti dia.

Namun sekarang, seiring waktu keputusan semakin menjauh seperti nasib pemotongan pajak di era Bush—akankah tarif pajak kembali ke tingkat seperti era Clinton? Kemarahan orang-orang kaya Amerika telah melebar, dan juga dalam beberapa hal berubah karakternya.
Untuk satu hal, kegilaan sudah menjadi mainstream. Di satu waktu, seorang miliarder mengadakan jamuan sebuah acara makan malam. Pada saat yang sama, mengasihani diri sendiri antara mereka yang berkelas istimewa menjadi sangat diterima, bahkan nge-trend.
Partai Republik menggarisbawahi bahwa menaikkan pajak di kalangan atas akan menyakiti usaha kecil, tapi hati mereka tampaknya tidak begitu tulus. Sebaliknya, telah sering terdengar penolakan keras bahwa orang-orang yang membayar $ 400.000 atau $ 500.000 setahun sekali adalah mereka yang kaya. Dan di antara kaya yang tak bisa disangkal: itu uang mereka, dan mereka punya hak untuk menyimpannya. "Pajak adalah yang kita bayar untuk masyarakat beradab," kata Oliver Wendell Holmes—tapi itu sudah lama sekali.
Rakyat Amerika yang berpenghasilan tinggi, yang dianggap sebagai orang-orang paling beruntung di dunia, berkubang mengasihani diri sendiri, kecuali satu hal: mereka mungkin mendapatkan jalan mereka. Jangan pikirkan harga $ 700 juta untuk memperpanjang potongan pajak kelas atas: hampir semua Republikan dan beberapa Demokrat bergegas membantu kaum tertindas yang makmur.

Orang kaya selalu berbeda dari siapapun: mereka memiliki pengaruh lebih. Misalnya dalam masalah sumbangan kampanye. Tapi mereka juga merupakan masalah sosial, karena politisi menghabiskan banyak waktu bergaul dengan mereka. Jadi, ketika wajah orang kaya memberikan prospek membayar ekstra 3 atau 4 persen dari pendapatan mereka untuk pajak, politisi juga merasakan sakit yang sama. Mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih akut, daripada yang mereka merasakan ketika melihat keluarga yang kehilangan pekerjaan mereka, rumah-rumah mereka, dan harapan mereka.
Dan ketika perjuangan pajak berakhir, satu atau lain cara, orang-orang Amerika saat ini yang membela elit akan kembali menuntut pemotongan jaminan sosial dan bantuan kepada para penganggur. Amerika harus membuat pilihan sulit, mereka akan mengatakan, "Kita semua harus bersedia untuk berkorban."
Tapi ketika mereka mengatakan "kami," maksud mereka adalah "kalian." Pengorbanan hanya untuk rakyat kecil. (sa/thenewyorktimes)