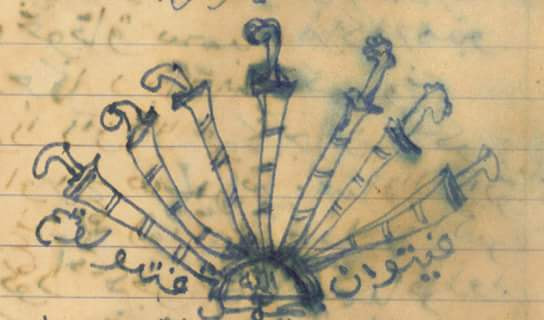Periode keempat, karena tidak mampu keluar dari krisis, akhirnya pada tahun 1998 Soeharto menyerahkan penyelesaian krisis ekonomi kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Di depan ‘dokter’ IMF, terbongkarlah borok-borok perekonomian Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi. Ternyata pemerintah punya utang luar negeri sebesar 60 miliar dolar. Ironisnya, para konglomerat Indonesia punya utang di luar negeri yang lebih besar dari pemerintahnya sendiri, yaitu sebesar 75 miliar dolar!
Periode keempat, karena tidak mampu keluar dari krisis, akhirnya pada tahun 1998 Soeharto menyerahkan penyelesaian krisis ekonomi kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Di depan ‘dokter’ IMF, terbongkarlah borok-borok perekonomian Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi. Ternyata pemerintah punya utang luar negeri sebesar 60 miliar dolar. Ironisnya, para konglomerat Indonesia punya utang di luar negeri yang lebih besar dari pemerintahnya sendiri, yaitu sebesar 75 miliar dolar!
Kreditor swasta luar negeri meminta bantuan dari pemerintah negaranya masing-masing untuk menagih piutang mereka yang macet pada konglomerat Indonesia. Pemerintah asing kemudian menalangi uang pinjaman para kreditor swasta, warga negaranya. Selanjutnya gantian, pemerintah negara asing itu menekan Indonesia untuk dapat mengambil-alih utang swasta, di antaranya lewat “dokter” IMF.
Akhirnya pemerintah mengambil-alih utang konglomerat kepada kreditor luar negeri. Pemerintah mengambil-alih tanggungjawab utang kepada luar negeri, sedang konglomerat yang punya utang ke luar negeri mengalihkan utangnya kepada pemerintah yakni BPPN. Berdasarkan Frankfurt Agreement, Juni 1998, pemerintah membayar utang bank swasta nasional dengan dana segar 1 miliar kepada bankir luar negeri tanpa verifikasi BPK/BPKP.
Begitu enak menjadi konglomerat Indonesia dan begitu tega pemerintahan Soeharto kepada rakyatnya. Para konglomerat itu berutang ke luar negeri tanpa minta persetujuan lebih dulu dari pemerintah, tetapi ketika utangnya macet, kewajibannya kemudian diambil-alih pemerintah, tentunya dengan uang milik rakyat yang kian miskin dan sengsara.
Utang konglomerat kepada luar negeri yaitu sebesar 75 miliar dolar. Dengan kurs Rp 8.000, jumlah itu mencapai Rp 600 triliun. Utang sebesar itulah yang harus ditanggung rakyat, padahal dengan biaya beberapa triliun rupiah saja krisis Aceh, Ambon-Maluku, Poso, Irian Jaya dan daerah-daerah lain bisa diselesaikan dengan pembangunan proyek-proyek sosial ekonomi yang memberdayakan rakyat.
Periode kelima, penjarahan dana rakyat melalui rekapitalisasi berlangsung selama 1998-1999. Adalah penting jika bank-bank BUMN milik pemerintah direkapitalisasi alias diberi suntikan tambahan modal untuk bisa melakukan aktivitas perbankan dengan normal. Tetapi bank-bank nasional swasta yang sudah menyelewengkan dana KLBI dan BLBI maupun melanggar BMPK untuk kepentingan usahanya sendiri kemudian direkapitalisasi. Apa gunanya bagi rakyat?
Soal rekapitalisasi bank-bank swasta nasional, pemerintah sudah terjebak Keppres No 24 dan No 26/ 1998. Langkah apapun yang akan dipilih, pemerintah harus memikul beban yang berat. Bila dilikuidasi, pemerintah harus menyediakan (mengeluarkan) biaya lebih dari Rp 600 triliun. Bila direkapitalisasi harus menyediakan biaya lebih dari Rp 400 triliun.
Untuk membiayai dana rekapitalisasi tersebut, pemerintah telah (dan akan) menerbitkan obligasi seluruhnya senilai Rp 430 triliun. Dari obligasi yang sudah diterbitkan dan sudah dimasukkan sebagai aset produktif bank-bank yang sakit, sebagaimana tercantum dalam penjelasan APBN tahun 2000, bunga obligasi yang akan dibayar oleh pemerintah dan telah dibebankan pada APBN tahun 2000 tercatat sebesar 42 triliun. Dan yang akan dibebankan pada APBN tahun 2001 berjumlah Rp 80 triliun.
Tapi ternyata Menko Ekuin Kwik Kian Gie menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka rekapitalisasi sudah menerbitkan obligasi sebesar Rp 650 triliun dengan bunga atas beban APBN 2000 sebesar Rp 42 triliun. Program rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi ini ternyata tidak mampu menggerakkan roda perekonomian nasional yang sudah lama lumpuh, hanya mampu memperbaiki posisi CAR-nya. Hal ini karena obligasinya tidak (atau kurang) likuid sehingga sulit dicairkan (dijual) di pasar modal. Sementara itu negara (rakyat) tetap harus menanggung beban bunganya.
Kebijaksanaan pemerintah mensubsidi para konglomerat lewat program kekapitalisasi perbankan sangat tidak adil dan melukai hati rakyat bila mereka tahu. Para konglomerat yang sudah terbukti membuat ekonomi Indonesia berantakan malah mendapat suntikan modal ratusan triliun rupiah (yang sebelumnya telah berhasil membobol uang rakyat melalui BLBI sebesar Rp 164, 54 triliun). Sementara subsidi untuk perekonomian rakyat banyak, seperti pengadaan pupuk untuk puluhan juta petani sebesar Rp 3 triliun saja malah dicabut.
Seharusnya pemerintah tidak boleh begitu saja mengalokasikan pengeluaran sejumlah dana sebagai biaya bunga obligasi pada APBN guna menyuntik bank-bank yang bermodal minus. Ini harus ada batasan karena ini menggunakan uang rakyat. DPR juga harus secara tegas menolak kebijakan pemerintah ini. Ketua BPK Satrio B Joedono dalam laporan investigasi BPK atas BLBI menyatakan bahwa negara terancam rugi Rp 138 triliun akibat dana BLBI yang disalurkan secara ngawur, baik oleh BI maupun bank swasta penerima BLBI.
Di republik ini memang aneh. Banyak bank-bank yang dilikuidasi, di-BBO-kan, di-BTO-kan, atau di-BBKU-kan atau yang semuanya itu artinya bangkrut, tapi para bankir (pemilik dan pengelolanya) hidup supermewah, bebas berkeliaran berpesta-ria, bagai kaum jetset kelas dunia.
Kalau keadaan ini dibiarkan, bukan hal yang mustahil para bankir nakal, para pejabat BI, dan para oknum penegak hukum ber-KKN dalam merampok uang rakyat melalui sistem dan jaringan perbankan nasional ini akan ramai-ramai diseret, dikeroyok, dan dibakar massa. Sekarang, hal ini belum terjadi karena sebagian besar rakyat Indonesia masih belum paham semua peristiwa ini, tidak tahu besarnya uang yang dirampok oleh para konglomerat dengan cara tindak kejahatan melalui sistem dan jaringan perbankan. Atau mungkin pula dibodohi tokoh-tokoh parpol yang memiliki kepentingan sesaat demi memperkaya diri dan keluarganya sendiri. (Bersambung/rd)