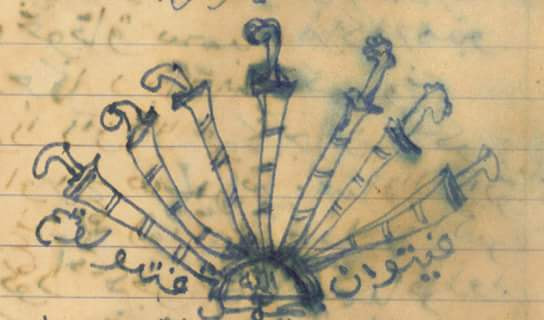Sejak diobralnya kekayaan alam Nusantara oleh para ekonomnya Suharto kepada berbagai korporasi asing di Swiss tahun 1967 tersebut, yang mana undang-undang tentang usaha penanaman modal dan sebagainya juga dirumuskan di sana sesuai kehendak dari pihak asing, maka sejatinya negeri kaya raya ini telah kembali ke alam penjajahan.
Sejak diobralnya kekayaan alam Nusantara oleh para ekonomnya Suharto kepada berbagai korporasi asing di Swiss tahun 1967 tersebut, yang mana undang-undang tentang usaha penanaman modal dan sebagainya juga dirumuskan di sana sesuai kehendak dari pihak asing, maka sejatinya negeri kaya raya ini telah kembali ke alam penjajahan.
Jika Bung Karno berusaha membangun nasional dan karakter bangsa ini dengan kemandirian secara ekonomi dan politik, maka oleh Jenderal Suharto prinsip tersebut diganti dengan ketergantungan dan penjajahan ekonomi dan politik oleh asing terhadap bangsanya sendiri.
Secara kasat mata, awal pemerintahan Orde Baru-nya Suharto ini memperlihatkan pembangunan fisik yang sungguh hebat dan cepat. Tahun 1970-an oil booming melanda negeri ini dan membuat segelintir elit penguasa dan pengusaha yang berkolusi menjadi makmur. Kunio Yoshihara menyatakan di dalam bukunya yang sempat dilarang oleh Orde Baru “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”, bahwa pembangunan yang terjadi di Indonesia merupakan pembangunan yang rapuh karena sepenuhnya disokong oleh utang.
Yoshihara juga menulis bahwa elit politik dan ekonomi di negeri ini bisa hidup makmur, di tengah lautan kemiskinan bangsanya, karena adanya KKN antara “Ali” dengan “Baba”. Ali di sini istilah terhadap para pejabat dan pengusaha melayu, sedangkan Baba merupakan istilah bagi cukong-cukong Cina yang diuntungkan oleh pejabat-pejabat birokrat dan penguasa Melayu tersebut. Dengan kata lain, elit penguasa negeri ini bisa hidup makmur dengan cara menikmati komisi dari usahanya menjual kekayaan alam negerinya sendiri kepada asing.
Para birokrat negeri ini hanya berperan sebagai semacam stempel bagi pengusaha untuk bisa terus mendapatkan keuntungan finansil dari upayanya itu. Arief Budiman, sosiolog Indonesia yang kini menetap di Australia di dalam bukunya “Krisis Tersembunyi dalam Pembangunan, Birokrasi-Birokrasi Pembangunan’ (1988) menulis, “Dari sepuluh kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat maka sembilannya merupakan kebijakan yang semata-mata menguntungkan dirinya sendiri”.

Hal yang paling mencolok terjadi pada pertengahan tahun 1990-an saat Bank Indonesia menggelontorkan kredit ratusan triliun rupiah kepada para konglomerat dengan skema “Kredit Likuiditas Bank Indonesia’ (KLBI) untuk membantu kesehatan usaha mereka. Uang rakyat dijadikan bancakan untuk para konglomerat yang ternyata juga meminjam dalam jumlah sangat besar kepada pihak asing asing.
Ada hal yang aneh dalam krisis ekonomi di tahun 1997. Pada medio 1996, setahun sebelum krisis dimulai, terjadi pemindahan dana secara besar-besaran dengan nominal lebih dari US$100 miliar “milik” swasta dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di Singapura. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya para konglomerat yang kebanyakan sipit itu sudah tahu—atau malahan bersekongkol—bahwa pialang Yahudi George Soros akan memborong dollar AS secara besar-besaran di tahun 1997 dari seluruh pasar mata uang Asia.
Rachmat Basoeki, Koordinator Front Anti Konglomerat Koruptor (FAKTOR) membagi kasus ini menjadi Tujuh periode Penjarahan Uang Rakyat, yakni:
• Periode pertama, 1985-1996: Penjarahan dana KLBI.
• Kedua, 1988-1996: Penjarahan oleh perbankan swasta via Pakto 88.
• Ketiga, 1998-1999: Penjarahan dana BLBI.
• Keempat, 1998: Utang dolar konglomerat ditanggung BPPN/rakyat.
• Kelima, 1998-1999: Penjarahan bunga deposito.
• Keenam, 1998-2000: Penjarahan dana rekapitalisasi.
• Ketujuh, 1998-2000: Penjarahan melalui BPPN.
Periode pertama,
Penjarahan dana KLBI, yang merupakan pengurasan kantong BI untuk mengisi kantong konglomerat, terjadi selama tahun 1985-1996. Ba’da tragedi Priok yang membuat masyarakat ketakutan untuk mengeluarkan kritik, Trio RMS (Radius Prawiro—Adrianus Mooy—JB Sumarlin) yang semuanya non-Muslim pada tahun 1985 secara diam-diam melalui BI meluncurkan skim Kredit Pembauran untuk industri. Ini kredit besar untuk industri tanpa agunan tambahan, karena agunannya adalah proyek industri yang dibiayai KLBI itu sendiri. Dengan alasan, mempercepat industrialisasi di Indonesia, kredit besar-besaran melalui KLBI dikucurkan pemerintah.
Sejak tahun 1985, di bawah kepemimpinan dewan moneter RMS (Radius-Mooy-Sumarlin) dengan operator Deputi Gubernur BI (d/h Direktur BI) Hendrobudiyanto, bermunculanlah konglomerat baru di Indonesia, akibat dikucurkannya KLBI. Presiden Soeharto merestui kebijakan moneter itu karena anak-anaknya juga mendapat guyuran KLBI.
Dalam periode 1985-1988, KLBI yang dikucurkan tidak kurang dari 100 triliun rupiah, jumlah yang pasti sulit dilacak karena terbakarnya gedung tinggi BI (Jalan Thamrin, Jakarta) yang penuh berisi dokumen ini pada Desember 1997 (disengaja?). Sebagian besar dokumen milik 15 bank yang dilikuidasi pada November 1997 ludes dilalap api, yang menyebabkan Tim Investigasi BPK dan BPKP mengalami kesulitan menelusuri pengucuran dan penggunaan KLBI/BLBI 15 bank tersebut. Jumlah Rp 100 triliun itu amat besar, mengingat waktu itu kurs dolar Amerika ‘cuma’ berkisar pada angka Rp 1.000. Dengan kurs satu dolar AS setara dengan Rp 9.000, – saja, maka jumlahnya menjadi Rp 900 triliun! Inilah jumlah uang rakyat Indonesia yang masuk ke kantong para konglomerat dalam skema KLBI! (Bersambung/rd)