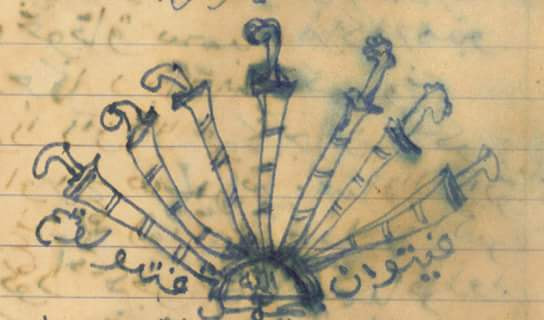Apa persoalan sangat besar yang dihadapi bangsa ini? Jawabannya adalah kemiskinan. Masalah ini diakibatkan oleh dua faktor utama yakni imperialisme negara-negara utara yang berjalan ratusan tahun hingga hari ini atas negeri kaya raya bernama Indonesia, dan kedua, tidak amanahnya (baca: pengkhianatan) yang dilakukan elit politik negeri ini sejak zaman kerajaan hingga zaman ustadz naik Bentley, padahal di tengah-tengah mereka terdapat lautan kemiskinan dan kesengsaraan.
Apa persoalan sangat besar yang dihadapi bangsa ini? Jawabannya adalah kemiskinan. Masalah ini diakibatkan oleh dua faktor utama yakni imperialisme negara-negara utara yang berjalan ratusan tahun hingga hari ini atas negeri kaya raya bernama Indonesia, dan kedua, tidak amanahnya (baca: pengkhianatan) yang dilakukan elit politik negeri ini sejak zaman kerajaan hingga zaman ustadz naik Bentley, padahal di tengah-tengah mereka terdapat lautan kemiskinan dan kesengsaraan.
Pengkhianatan elit politik di negeri ini disebabkan mereka tidak memiliki karakter. Jujur saja, para elit politik kita sejak zaman dulu hingga sekarang ini sangatlah pragmatis dan oportunistik, sehingga mereka selalu saja mendahulukan kepentingan keluarga, kelompok, dan golongannya ketimbang rakyat banyak. Dalam hal ini mungkin Presiden pertama RI Bung Karno merupakan perkecualian.
Ketika berbagai kerajaan masih bercokol di Nusantara, sistem feodalisme membuat rakyat banyak hidup dalam kebodohan dan kemiskinan dan sebaliknya, para bangsawan, termasuk raja serta keluarganya hidup dalam kelimpahan harta benda dan segala kenikmatan dunia.
Para penjajah dari negeri-negeri utara melihat bahwa kaum elit ini bisa diajak bersekutu untuk memerangi rakyat banyak. Para penjajah kemudian mempertahankan sistem ini dengan merangkul para bangsawan untuk dijadikan sekutu dan bersama-sama menghisap kekayaan negeri ini dengan menunggangi rakyat banyak. Hal tersebut dilakukan oleh Portugis, VOC, Belanda, Jepang, dan mulai tahun 1967—saat Jenderal Suharto berkuasa dengan mengkudeta Bung Karno—semua kekayaan alam Nusantara mulai dijual dengan harga sangat murah kepada jaringan korporasi multinasional Yahudi yang berpusat di Amerika dan Eropa. Washington sendiri menyebut jatuhnya kekuasaan Bung Karno sebagai “Hadiah besar dari Timur” dan dirayakan dalam acara pesta yang sangat meriah. Tangan CIA memang berlumuran darah dalam peristiwa ini.
Ironisnya, setelah 32 tahun berkuasa, setelah Jenderal Suharto lengser, warisan Jenderal Suharto ini terus dipelihara dalam era reformasi dan bahkan kini didukung partai-partai politik yang mengaku reformis padahal kenyataannya Suhartois. Silakan baca daftar partai politik apa saja yang mendukung pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil, misalnya, atau partai politik mana saja yang mendukung dinaikkannya harga BBM negeri ini dengan harga BBM New York sesuai Konsensus Washington, atau partai politik mana saja yang membatalkan gugatan parlemen terhadap kasus BLBI yang telah merampok uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua Suhartois.
Bisa jadi, sebab itulah ketika Jenderal Suharto meninggal, ada sejumlah elit partai yang memohon-mohon agar bangsa ini memaafkan dosa-dosa Suharto, bahkan sampai menyambangi rumah SBY di Cikeas dan memasang iklan besar di suratkabar nasional segala.
Siapa pun yang sadar sejarah pasti tahu jika Orde Baru Suharto tumbuh di atas genangan darah jutaan rakyatnya sendiri yang dibantai pada pekan ketiga Oktober 1965 hingga bulan-bulan pertama tahun 1966, sebuah kejahatan yang melebihi kebiadaban rezim Polpot di Kamboja. Sarwo Edhie, mertua Presiden SBY yang di tahun 1965-1966 menjadi algojo-nya Suharto dengan bangga menyebut angka 3 juta rakyat Indonesia yang dibunuhnya (John Pilger: The New Rules of the World). Sejarah bangsa ini diam seribu bahasa atas tragedi besar tersebut.
Dan ingat, kekuasaan tiranik Orde Baru bisa langgeng selama 32 tahun dengan melakukan pembunuhan terhadap ribuan umat Islam di Aceh, Lampung, Priok, dan sebagainya. Umat Katolik pun mereka bantai dalam tragedi pekuburan Santa Cruz di Dili pada Nopember 1991.
Dari Berdikari ke Ketergantungan
Selama 32 tahun masa kekuasaannya dan diteruskan selama 10 tahun era reformasi, bangsa ini terus dibohongi oleh para elit negara tentang peristiwa 1965. Penafsiran tunggal atas tragedi di tahun itu adalah pemberontakan PKI atas NKRI yang Pancasilais. Padahal, sekarang ini dokumen-dokumen CIA telah banyak yang dideklasifikasikan dan mengakui jika tragedi 1965 itu merupakan hasil konspirasi CIA bersama segelintir orang-orang Indonesia yang masuk dalam kelompok Klandestin bernama Van Der Plas Connection yang tersebar di dalam tubuh AD, ada yang menyusup ke PKI, dan para ekonom didikan Universitas Berkeley AS atas arahan Guy Pauker, dari Rand Corporation dan juga tokoh CIA.
 Tujuan sesungguhnya dari gerakan Van der Plas Connection adalah menjadikan bangsa kaya raya, sebuah negeri Muslim terbesar di dunia ini, sebagai sapi perahan kekuatan imperialisme Barat yang dikomandoi AS. Bung Karno merupakan penghalang besar bagi upaya jahat tersebut (ucapan Bung Karno yang terkenal: Go to Hell With Your Aids!”) sehingga harus disingkirkan. AS mempergunakan strategi memanfaatkan anak negeri ini yang bersedia diajak kerjasama untuk menjual bangsanya sendiri. AS membina segelintir elit Indonesia lewat dua bidang: militer dan teknokrat.
Tujuan sesungguhnya dari gerakan Van der Plas Connection adalah menjadikan bangsa kaya raya, sebuah negeri Muslim terbesar di dunia ini, sebagai sapi perahan kekuatan imperialisme Barat yang dikomandoi AS. Bung Karno merupakan penghalang besar bagi upaya jahat tersebut (ucapan Bung Karno yang terkenal: Go to Hell With Your Aids!”) sehingga harus disingkirkan. AS mempergunakan strategi memanfaatkan anak negeri ini yang bersedia diajak kerjasama untuk menjual bangsanya sendiri. AS membina segelintir elit Indonesia lewat dua bidang: militer dan teknokrat.
Para perwira yang kebanyakan dari AD diberi pelatihan militer di AS di Fort Leavenworth dan Fort Bragg. Sedangkan untuk para teknokrat, kebanyakan ekonom dan dari PSI, dididik di Berkeley University, Cornell, MITT, Harvard, dan sebagainya. Hal ini telah dimulai sejak tahun 1950.
Setelah Soekarno dan para pendukungnya dihabisi, dua ujung tombak AS ini—para perwira AD dan para ekonom binaan Amerika—memasuki pusat kekuasaan. Dan benar saja, di awal kekuasaannya, Jenderal Soeharto lengsung mengundang IMF dan Bank Dunia untuk merampok negeri ini. Pada Nopember 1967, Suharto juga mengirim satu tim ekonom—yang disebut Rockefeller sebagai “The Berkeley Mafia”—ke Swiss menemui para gembong korporasi multinasional yang antara lain Rockefeller sendiri. (bersambung/rd)