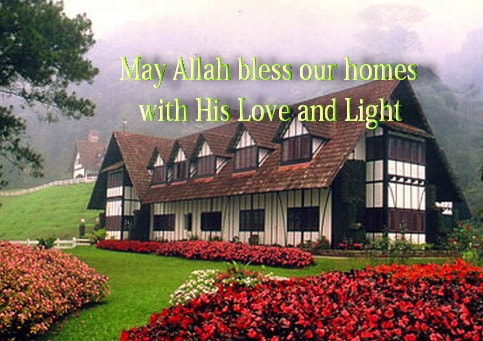Menjelang Pemilu 2014, isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan. Kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan calon anggota legislatif mulai diberlakukan pada Pemilihan Umum 2009. Kini, setelah hampir lima tahun berlalu, bagaimanakah kiprah anggota perempuan di parlemen? Apakah kiprah perempuan di parlemen telah menyelesaikan masalah-masalah perempuan?
Menjelang Pemilu 2014, isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan. Kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan calon anggota legislatif mulai diberlakukan pada Pemilihan Umum 2009. Kini, setelah hampir lima tahun berlalu, bagaimanakah kiprah anggota perempuan di parlemen? Apakah kiprah perempuan di parlemen telah menyelesaikan masalah-masalah perempuan?
Prokontra muncul terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Bahkan Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Poin-poin tersebut dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b,11d, 24 ayat 1c-d dan ayat 2.
Pada Pemilu 1999, proporsi perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya 9,2 persen dari total jumlah anggota. Tahun 2004, proporsinya meningkat jadi 11,81 persen. Peningkatan cukup besar terjadi pada Pemilu 2009, 18 persen. Namun, apakah angka tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan di Senayan? Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu memperlihatkan, kehadiran perempuan di DPR dinilai publik belum membawa perubahan nyata di masyarakat. Secara umum, 62,5 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja para perempuan politisi di Senayan. Sejumlah sektor strategis pun disorot publik. Salah satunya adalah soal pekerja migran. Enam dari sepuluh responden menyatakan tak puas atas upaya perempuan anggota parlemen dalam menghasilkan perundang-undangan yang melindungi para perempuan pekerja migran. Bahkan, kerja perempuan anggota legislatif untuk memajukan pendidikan pun dinilai masih kurang memuaskan oleh separuh bagian responden. Padahal kuota 30 persen bagi wanita, oleh wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli Diharapkan, dapat merubah kebijakan keuangan terkait anggaran yang lebih progender.
Ani Sucipto pengamat politik dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), dalam diskusi empat pilar bertema “Penguatan Peran Politik Perempuan” di Ruang Perpustakaan MPR RI, Jakarta, Senin (18/3). menilai, kinerja perempuan di Parlemen belum efektif secara substantif meski ada peningkatan jumlah pada periode 2009-2014 ini. Masih tingginya kasus yang mendera perempuan, seperti KDRT dan angka kematian ibu (AKI), menunjukkan keterwakilan perempuan di Parlemen belum optimal. Keterwakilan mereka belum mampu mengubah citra dan kinerja Parlemen serta belum mampu menyuarakan isu jender dalam proses pembuatan perundang-undangan
Bagaimana perempuan di parlemen bisa berdaya jika partai politik (parpol) tidak serius merekrut perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Mereka hanya menjadikan perempuan pelengkap penderita guna memenuhi kuota seperti yang dituntut undang-undang. Ani lebih jauh menjelaskan, saat ini parpol masih terjebak pada angka 30 persen perempuan seperti perintah UU No 8 tahun 2012 tentang Parpol dalam pencalonan anggota legislatif (caleg). Parpol pun kemudian asal merekrut perempuan berdasarkan jenis kelamin, tidak mengutamakan kader dengan representasi basis dan kualitas. Parpol hanya merekrut perempuan karena modal popularitas, seperti artis, pengusaha, dan kelompok pragmatis lainnya.
Perjuangan Kesetaraan Jender
Kebijakan afirmasi (affirmative action) atau kebijakan yang bersifat mendorong perempuan dalam bidang politik diterapkan, karena dunia politik masih diyakini kalangan feminis sebagai dunia yang arogan dan patriarkis. Akibatnya, komposisi perempuan di lembaga perwakilan tidak seimbang dengan jumlah penduduk perempuan.Keputusan yang dikeluarkan parlemen masih dianggap diskriminatif bagi perempuan.
Di Indonesia, gerakan afirmasi dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, Jaringan Perempuan Politik, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan 38 LSM sejak tahun 2001. Peneliti Pusat Kajian Politik UI, Ani Sucipto mengatakan, kebijakan afirmasi diperlukan karena adanya kesenjangan jender; baik dari segi kuantitas atau keterbatasan kultur pada perempuan yang mengharuskannya mengurus anak dan keluarga ..
Demokratisasi demi Sekularisasi
Kebijakan afirmasi perempuan dalam politik adalah hajat Barat yang diinisiasi dan dikentalkan oleh PBB, seperti tercantum dalam Beijing Platform for Action (BPfA ) tahun 1995. Demokrasi memang menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Dalam Bali Democracy Forum 8-9 November 2012 PM Australia Julia Gillard menegaskan peran perempuan Indonesia sebagai kunci proses demokratisasi. Gillard telah menjanjikan bantuan $ 1.750.000 untuk menjalankan lembaga demokrasi di Indonesia selama tiga tahun ke depan. Dia ingin menggunakan program itu untuk mendorong lebih banyak perempuan memasuki dunia politik. (http://www.news.com.au, 8/11/2012).
Pemerintah Indonesia, menjadikan demokrasi menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang politik. Demi menunjukkan komitmen itu, Bappenas telah mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI menjadi salah satu target sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Walaupun Indonesia masih harus membuktikan dirinya sebagai negara demokratis karena capaian nilai IDI-nya masih rendah. Perlu diketahui, nilai IDI tahun 2010 adalah 63.17, turun dari capaian tahun 2009, yakni 67.3.
Tiga aspek penting yang diukur dalam IDI adalah aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Untuk menuju negara yang demokratis, pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat inklusif. Karena itu salah satu variabel yang dinilai dalam aspek kebebasan sipil adalah kebebasan dari diskriminasi jender. Begitu pula hak politik untuk memilih dan dipilih, variabelnya adalah prosentase perempuan yang dipilih menjadi anggota DPRD. Adapun penilaian lembaga demokrasi secara khusus menyorot persentase perempuan dalam kepengurusan parpol di provinsi. Di antara tiga aspek itu, hak-hak politik menyumbang nilai terendah (54.6 pada tahun 2009, turun menjadi 47.87 pada tahun 2010). Karena itu, dunia internasional butuh pembuktian dari Indonesia bahwa perempuan menjadi agen penting bagi upaya demokratisasi melalui peningkatan jumlah mereka di Parlemen.
Tujuan peningkatan jumlah kuota perempuan adalah dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan UU yang pro perempuan. Kalangan jender berpendapat, masih tingginya kekerasan terhadap perempuan disebabkan implementasi UU No. 23/2004 tentang PKDRT belum efektif. Selain itu, perempuan dianggap akan mempermudah proyek legislasi penyusunan peraturan responsif jender. DPR masih dianggap punya pekerjaan rumah untuk melakukan revisi peraturan yang dianggap bias jender seperti UU Perkawinan No.1 tahun 1974, revisi KUHAP, Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta meloloskan aturan pro jender seperti RUU Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender. Padahal beberapa produk peraturan itu, selain ditargetkan untuk kepentingan ekonomi, justru diciptakan dengan tujuan mempersoalkan hukum-hukum Islam.
Indonesia didesak untuk membentuk peraturan perundang-undangan demi mengubah perilaku sosial dan budaya yang tidak mendukung kesetaran jender. Beberapa amalan yang bersumberkan syariah Islam menjadi poin yang ingin mereka ubah. Meneg PP dan PA Linda Gumelar juga mengatakan saat ini tantangan yang dihadapi adalah kendala kultural. Kendala ini ditandai dengan adanya pola pikir patriarki yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku individu dan kelompok. Mereka memang tidak menuding hidung kita. Namun, rentetan pernyataan yang dikeluarkan para feminis di awal tahun 2013 mengarahkan masyarakat Indonesia tentang betapa buruknya praktik sunat perempuan, kawin siri dan nikah dini, yang sering dikaitkan dengan syariah Islam. Mereka menginginkan Indonesia makin sekular melalui penetapan dan penerapan produk undang-undang.
Solusi Masalah Perempuan
Kuota tinggi untuk perempuan di Parlemen tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi perempuan umumnya, melainkan hanya menguntungkan perempuan kelas elit. Kalaupun kuota tersebut mencapai 100% tidak akan ada bedanya bagi para perempuan, karena mereka hidup di bawah sistem kapitalis korup yang menindas dan inkompeten.
Inkompetensi undang-undang buatan manusia itu terbukti nyata. Walaupun DPR telah melegalisasi UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak sejak tahun 2002, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menetapkan tahun 2013 ini sebagai tahun darurat kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang itu gagal melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh para pelindung mereka.
Apalagi UU yang dibuat tidak pernah berpihak pada kemaslahatan rakyat. Ketua DPP PPP Reni Marlinawati Amin menilai DPR tidak lagi punya keterkaitan moral dengan masyarakat yang mereka wakilinya. “DPR tidak punya kapasitas membuat UU demi kepentingan rakyat. Yang ada sekarang pembuatan UU hanya untuk kepentingan pemodal saja..,” ucapnya (Pikiran-rakyat.com, 8/3/2013).
Begitulah sistem perundang-undangan yang dibuat dengan semangat sekularis. Tak akan mungkin perempuan terjamin hidupnya karena hak-hak mereka dapat dihapus sesuai keinginan penguasa. Apalagi konsep kesetaraan jender yang dipaksakan Barat untuk diadopsi semua negara nyatanya hanya menciptakan halusinasi akan keadilan dan kesejahteraan. Justru Barat menuai buah dari liberalisasi perempuan akibat penerapan ide kesetaraan jender. Tingginya angka kekerasan dan penyerangan seksual yang dialami perempuan dan anak-anak, bahkan dilakukan oleh individu dari lembaga terhormat seperti Uskup atau anggota Parlemen membuktikan hal itu. Masihkah kita mempercayai sistem buatan manusia, yang mencampuradukkan segala konsep untuk mengatur kehidupannya? Padahal Allah SWT telah menyediakan seperangkat hukum yang kompeten, adil, komprehensif dan pasti menjamin kesejahteraan. Itulah solusi bagi semua masalah manusia, bukan hanya perempuan.
(Dini Sumaryanti, Pengamat Perempuan)